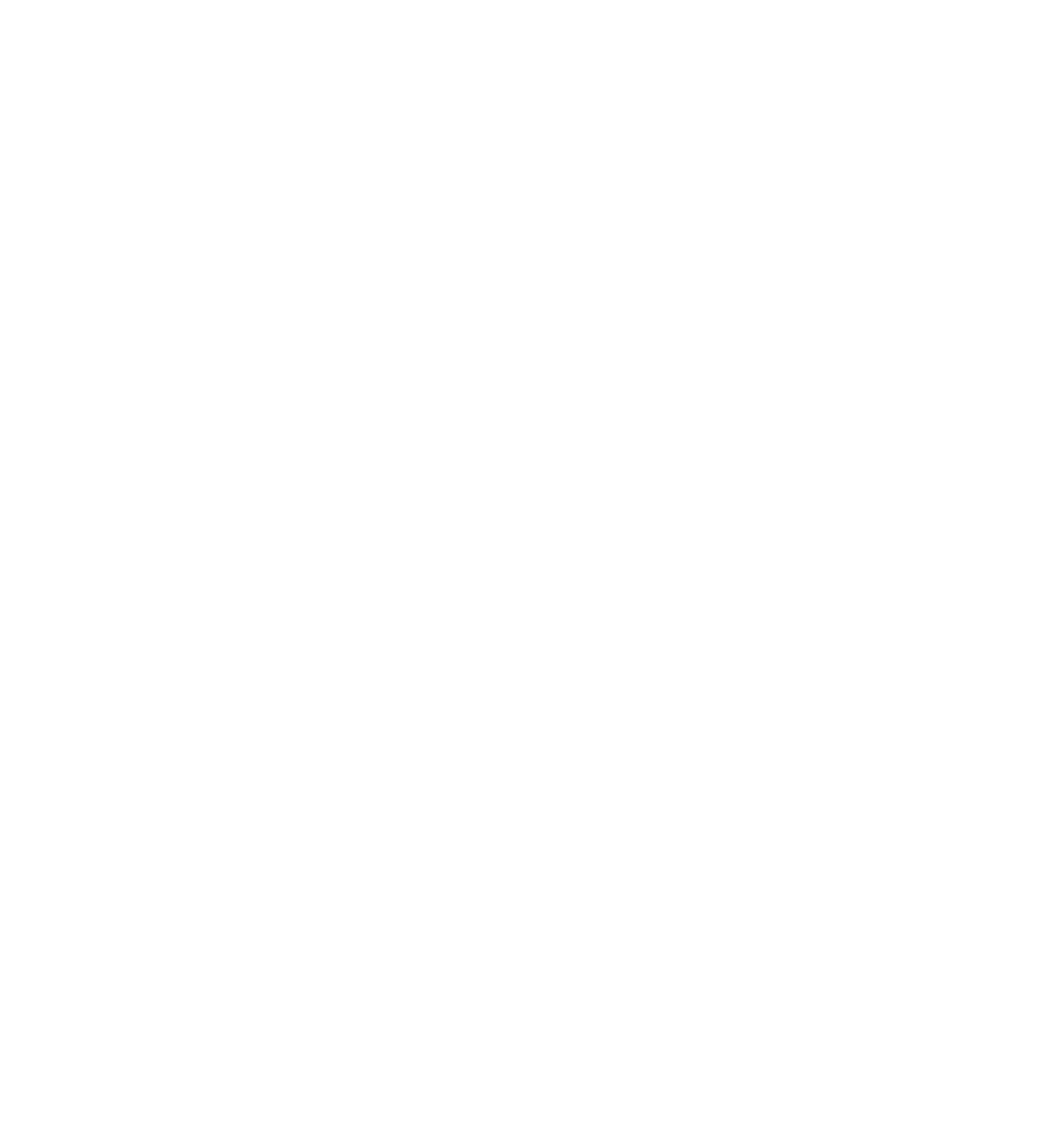Menanti Revisi UU: Pemilu Sebagai Panggung Kedaulatan Rakyat
Menanti Revisi UU: Pemilu Sebagai Panggung Kedaulatan Rakyat
Oleh Jemris Fointuna
Pemilu adalah momentum di mana seluruh rakyat dikonsolidasikan ke dalam satu ruang kebangsaan yang utuh, melampaui segmentasi sosial dan partisi golongan. Dalam logika demokrasi, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai pernyataan (deklaratif) bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Posisi rakyat tidak boleh direduksi menjadi simbolik semata, melainkan harus hadir nyata sebagai pusat pengambilan keputusan. Bertentangan dengan kehendak rakyat sama dengan meruntuhkan kepercayaan publik (public trust) dan pada akhirnya membuka ruang bagi public recall di masa depan. Dengan kata lain, Pemilu adalah bentuk nyata dari pactum unionis (perjanjian kesatuan) dan pactum subjectionis (perjanjian penyerahan diri), di mana rakyat bersepakat membentuk tatanan politik sekaligus menyerahkan mandatnya pada penyelenggara negara.
Dalam konteks pengesahan partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu, rakyat berperan sebagai juru kunci utama. Aturan mewajibkan setiap Parpol memiliki basis konstituen di berbagai tingkatan wilayah serta membuktikan militansinya melalui kepemilikan KTA. Prinsip kesukarelaan (voluntarysm) yang menjadi dasar keanggotaan partai menunjukkan ruang kebebasan rakyat untuk bergabung, tetapi begitu menjadi anggota, seseorang terikat pada statuta partai. Banyak partai akhirnya gagal memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu karena tidak mampu membuktikan legitimasi rakyat yang menjadi fondasi keberadaannya.
Ketika tahapan pencalonan dimulai, ruang ekspresi rakyat semakin terbuka lebar. Hampir semua Parpol mengakomodasi beragam latar belakang calon, mulai dari politisi, akademisi, pengusaha, aktivis, buruh, ibu rumah tangga, budayawan, artis, hingga petani dan pekerja informal. Dengan modal KTA, peluang mencalonkan diri terbuka. Fenomena ini memperlihatkan Pemilu sebagai arena sosial yang menyatukan berbagai aspirasi rakyat. Namun, di balik keterbukaan itu, ada paradoks: keterlibatan rakyat yang tampak luas bisa saja hanya menjadi ornamen prosedural, di mana rakyat dijadikan obyek mobilisasi politik, bukan subyek yang sungguh berdaulat.
Strategi Parpol dalam menyatukan kekuatan rakyat pada tahap pencalonan kerap memberi efek kejut pada hasil pemungutan suara. Banyak calon rela meninggalkan profesi mapan demi masuk ke gelanggang politik, seakan-akan jabatan hasil Pemilu adalah segalanya. Padahal jabatan itu hanya berlangsung lima tahun, dengan segala risiko hukum dan politik yang menyertainya. Pola ini memperlihatkan daya hipnosis Pemilu, tetapi sekaligus menyimpan bahaya ketika rakyat hanya diposisikan sebagai alat legitimasi formal tanpa dijamin ruang kontrol berkelanjutan.
Di sisi lain, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) memikul tanggung jawab besar. Mereka mengkonsolidasikan hak rakyat menjadi daftar pemilih yang sah melalui kriteria ketat seperti usia, status pernikahan, kepemilikan identitas, dan ketidakikutsertaan sebagai aparat negara. Setiap deviasi dalam proses ini berpotensi menghilangkan hak rakyat untuk memilih, yang bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi dan sila keempat Pancasila. Ketika data pemilih kacau, kedaulatan rakyat terguncang, dan Pemilu berisiko kehilangan legitimasinya.
Ekspektasi pasangan calon, Parpol serta calon anggota DPD terhadap kinerja penyelenggara Pemilu begitu besar, dengan menegaskan narasi “Suara Rakyat Suara Tuhan.” Narasi ini mengandung makna mendalam bahwa setiap suara harus dihargai sebagai mandat ilahi yang melahirkan legitimasi politik. Pada tahapan ini, posisi rakyat khususnya pemilih ditempatkan sebagai King and Queen, karena merekalah mandataris kedaulatan yang mewarisi hak untuk ikut memilih. Sedikit saja terjadi deviasi berpotensi menghilangkan hak pilih rakyat. Konsekuensi logis dari kelalaian mengelola data pemilih mengakibatkan hilangnya public trust. Dalam konteks yang lebih luas, penyelenggara Pemilu dianggap melakukan contempt of election berupa pelanggaran Konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila, pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
Kampanye kemudian menjadi ruang interaksi intensif antara rakyat dan peserta Pemilu. Secara ideal, kampanye menjadi wadah simbiosis mutualisme, tempat aspirasi rakyat bertemu dengan visi dan program politik. Namun, bila kampanye hanya dijalankan sebagai instrumen untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, maka rakyat kembali direduksi menjadi objek persuasi. Pada titik ini, ada bahaya bahwa Pemilu lebih berfungsi sebagai panggung pencitraan ketimbang arena pemberdayaan rakyat.
Sistem proporsional terbuka memang menegaskan prinsip one man, one vote, one value. Nilai suara seorang buruh setara dengan nilai suara seorang presiden. Kesetaraan inilah yang membuat rakyat merasa terhormat, karena suaranya tidak kalah berharga dengan suara elite. Namun, sejarah Pemilu Indonesia menunjukkan partisipasi rakyat tidak pernah mencapai 100 persen. Angka partisipasi tertinggi justru terjadi pada Pemilu 1971 di era otoritarian dengan 96,6 persen, namun ironisnya ini adalah masa ketika demokrasi masih bersifat semu. Angka tinggi itu bukan lahir dari partisipasi sejati, melainkan dari kontrol negara yang kuat. Inilah gambaran paling jelas dari pseudo demokrasi, partisipasi rakyat hanya tinggi di atas kertas, tetapi nihil kedaulatan substantif.
Kini, setelah DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-5 menyetujui 67 RUU prioritas, termasuk RUU Pemilu dan RUU Pemilihan Kepala Daerah, publik kembali mempertanyakan posisi rakyat. Apakah setelah kodifikasi UU ini rakyat tetap diposisikan sebagai pemegang kedaulatan, ataukah justru hanya sebagai penggembira demokrasi? Apabila revisi undang-undang lebih diarahkan pada penekanan teknokrasi prosedural seraya mengurangi ruang partisipasi substantif rakyat, maka yang akan lahir bukanlah demokrasi yang menghidupi rakyat, melainkan sebentuk pseudo demokrasi yang hanya menampilkan kulit luarnya. Demokrasi kehilangan vitalitasnya ketika kedaulatan rakyat dipersempit menjadi sekadar legitimasi formal, tanpa jaminan ruang artikulasi aspirasi yang otentik.
Jika ditelisik lebih jauh pada substansi pasal-pasal yang berpotensi diubah, problematika segera tampak. Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) selama ini hanya berfungsi mengonsolidasikan dominasi partai besar dan menutup kemungkinan lahirnya alternatif politik baru. Konsekuensinya adalah rakyat kehilangan keberagaman pilihan, padahal pluralitas politik merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 yang menghapus threshold tersebut karenanya dapat dibaca sebagai koreksi historis. Namun, momentum ini masih menyimpan risiko. Bila revisi undang-undang justru kembali memasukkan mekanisme pembatasan lain yang pada hakikatnya menyerupai threshold, maka esensi putusan MK akan tereduksi, dan kedaulatan rakyat kembali dipersempit. Begitu pula wacana kembalinya sistem proporsional tertutup yang menempatkan daftar calon sepenuhnya dalam kendali elite partai. Langkah ini sesungguhnya menegasikan esensi kedaulatan rakyat, karena pemilih tidak lagi memiliki keleluasaan menentukan secara langsung siapa yang akan mewakili kepentingannya di parlemen.
Lebih jauh lagi, apabila verifikasi partai politik diperketat tanpa disertai mekanisme yang inklusif, maka lanskap politik yang tercipta cenderung semakin oligarkis. Partai-partai kecil yang kerap menjadi kanal artikulasi bagi aspirasi alternatif rakyat akan kesulitan tampil dalam kontestasi. Padahal, keberadaan mereka justru penting sebagai penyeimbang hegemoni partai besar serta sebagai indikator sejauh mana demokrasi mampu menampung keragaman suara warga. Dengan demikian, revisi yang tidak sensitif terhadap dimensi kedaulatan rakyat berpotensi menggeser demokrasi Indonesia dari ranah substantif menuju prosedural semata. Semua ini berpotensi memundurkan kualitas demokrasi kita, menjadikannya hanya sebagai etalase prosedural yang indah dilihat, tetapi kosong makna.
Bahaya pseudo demokrasi terletak pada kenyataan bahwa wajah luar tetap menampilkan mekanisme demokratis: Pemilu berlangsung, rakyat datang ke TPS, hasil diumumkan. Namun, di balik ritual itu, substansi kedaulatan rakyat perlahan terkikis. Demokrasi hanya menjadi pesta lima tahunan, sementara ruang kontrol rakyat di antara periode itu tertutup rapat. Rakyat sekadar dipanggil hadir sebagai legitimasi formal, tetapi suara kritisnya dibatasi, bahkan cenderung dibungkam.
Oleh karena itu, revisi UU Pemilu bukan hanya soal harmonisasi regulasi, melainkan juga soal menjaga substansi kedaulatan rakyat. Penantian publik terhadap UU baru sejatinya adalah penantian terhadap jawaban, apakah bangsa ini setia pada amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, atau justru tergelincir kembali ke masa lalu ketika demokrasi hanya formalitas. Jika arah revisi menjauh dari rakyat, maka Pemilu Indonesia akan jatuh ke dalam pseudo demokrasi, hanya meriah di permukaan, tetapi kehilangan ruh kedaulatan di dalamnya.
![]()
![]()
![]()