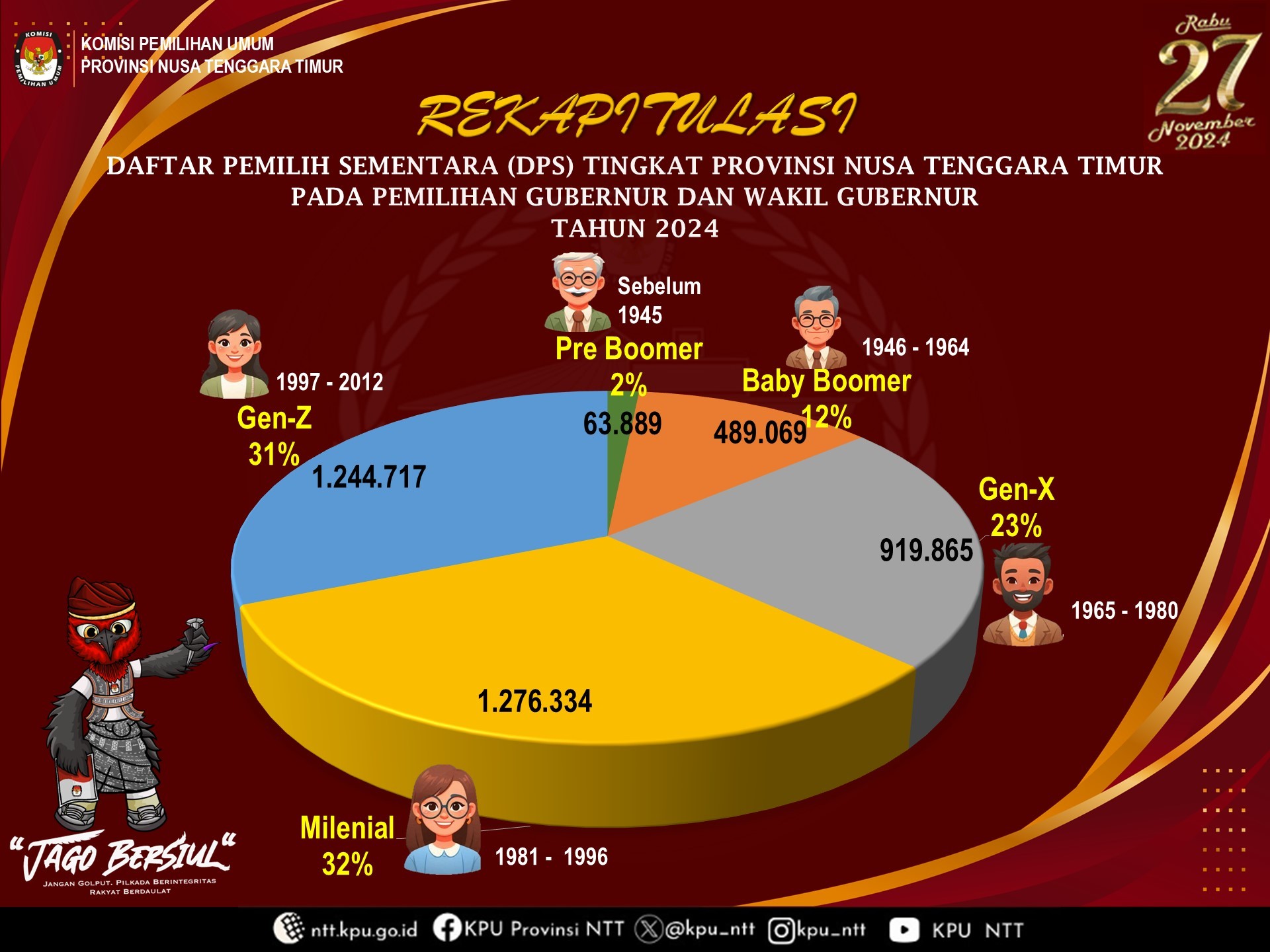KPU Provinsi NTT Gelar Rapat Pleno Rutin, Bahas Isu Strategis dan Program Kerja 2026
Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur gelar Rapat Pleno Rutin pada Senin (5/1/26) di Aula KPU Provinsi NTT. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna dan diikuti Anggota KPU Lodowyk Fredrik, Baharudin Hamzah, Elyaser Lomi Rihi dan Petrus Kanisius Nahak, serta para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan jajaran sekretariat. Rapat pleno membahas tindak lanjut hasil rapat pleno sebelumnya, serta membahas berbagai isu strategis. Pada Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, disampaikan progres pengelolaan akun coretax, dan digitalisasi Pengelolaan arsip. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM menegaskan Program KPU Mengajar, Kopi Parmas akan terus dilanjut sebagai bentuk inovasi kegiatan yang dilkakukan oleh KPU Provisi NTT, Pelatihan SIMPEL untuk jajaran Sekretariat, Bimtek penulisan berita dan persiapan kegiatan Latsar CPNS KPU. Sementara itu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi membahas penyusunan laporan kinerja, survei kepuasan masyarakat, serta matriks kinerja Tahun Anggaran 2026. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, rapat pleno membahas pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Semester II Tahun 2025, termasuk perkembangan dan validasi data kepengurusan partai politik. Pada Divisi Hukum, rapat pleno membahas progres pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). ....

Apel Pagi Perdana 2026, KPU NTT Teguhkan Disiplin dan Profesionalisme
Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar apel pagi perdana tahun 2026 di halaman Kantor KPU Provinsi NTT, Senin (5/1/2026). Apel tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna. Dalam arahannya, Jemris menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi tahun yang penuh harapan bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab menjaga nilai-nilai luhur demokrasi. “Di tengah berbagai dinamika politik yang terjadi secara nasional, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap teguh, utuh, solid, dan harmonis dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” ujar Jemris. Ia juga mengingatkan bahwa apel pagi menjadi bentuk komitmen KPU Provinsi NTT untuk terus memperkuat disiplin, kekompakan, dan profesionalisme sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas. Di akhir arahannya Jemris menghimbau seluruh jajaran agar menjaga kesehatan sebagai bagian penting dalam mendukung kinerja dan pelayanan kelembagaan. Menurutnya, kondisi fisik yang prima menjadi modal utama dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan secara profesional. Apel pagi tersebut diikuti oleh Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie S. W. Hege, para anggota KPU Provinsi NTT Lodowyk Fredrik, Baharudin Hamzah, dan Petrus Kanisius Nahak, serta pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh staf Sekretariat KPU Provinsi NTT. ....

Apel Rutin KPU NTT, Jemris Fointuna Dorong Semangat dan Kinerja Hingga Akhir Tahun
Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Apel rutin pada Senin, (29/12), di halaman Kantor KPU Provinsi NTT. Apel dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, didampingi Anggota KPU Provinsi NTT, Elyaser Lomi Rihi, serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT, Melanie S. W. Hege dan diikuti oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh staf sekretariat KPU Provinsi NTT. Dalam arahannya, Jemris Fointuna menyampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai, agar tetap menjaga semangat dan komitmen dalam menjalankan kewajiban, khususnya terkait pelaksanaan dan tindak lanjut agenda-agenda dalam rapat pleno rutin. Menurutnya, konsistensi dan tanggung jawab bersama sangat diperlukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan optimal hingga akhir tahun. ....

Pimpin Rapat Pleno, Ketua KPU NTT Tekankan Profesionalitas dan Akuntabilitas
Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Rapat Pleno Rutin pada Senin (29/12). Rapat dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTT Jemris Fointuna, didampingi Anggota KPU Provinsi NTT, Lodowyk Fredrik, Elyaser Lomi Rihi kemudian Baharudin Hamzah dan Petrus Kanisius Nahak yang juga tergabung secara daring, turut hadir Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT, Melanie S. W. Hege serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Serta seluruh jajaran Sekretariat KPU Provinsi NTT. Rapat pleno membahas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya serta sejumlah agenda strategis lintas divisi menjelang akhir tahun anggaran. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik melaporkan pengelolaan arsip. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM menyampaikan rencana keberlanjutan program KPU Mengajar serta pemenuhan jam pelatihan ASN melalui aplikasi SIMPEL. Sementara itu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi melaporkan persiapan laporan kinerja, survei kepuasan masyarakat, serta penyesuaian matriks kinerja Tahun Anggaran 2026. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan menyampaikan perkembangan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, sedangkan Divisi Hukum dan Pengawasan menekankan penguatan disiplin ASN dan percepatan pelaporan SPIP Semester II Tahun 2025. Rapat pleno ditutup dengan komitmen KPU Provinsi NTT dalam menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola kelembagaan yang baik. ....

Perkuat Peran PPID, KPU Provinsi NTT Ikuti Rakor Nasional KPU Tahun 2025
Jakarta, ntt.kpu.go.id - Anggota KPU Baharudin Hamzah bersama Plt.Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Melanie S. W. Hege mengikuti Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Tahun 2025 dengan agenda “Konsolidasi dan Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik”. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, di Hotel Luwansa Jakarta yang berlangsung selama tiga hari, Sabtu hingga Senin (20–22/12). Rapat koordinasi dibuka oleh Anggota KPU Republik Indonesia Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, August Mellaz. Dalam sambutannya, August menekankan pentingnya penguatan peran PPID sebagai garda terdepan layanan keterbukaan informasi publik sekaligus instrumen strategis dalam mendukung pendidikan pemilih berkelanjutan di tengah tantangan disinformasi dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI, Cahyo Ariawan, yang memaparkan penguatan kapasitas PPID melalui e-Learning sebagai sarana peningkatan pemahaman hak atas informasi, pelayanan informasi publik, serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Alamsyah Saragih menegaskan bahwa pengecualian informasi publik harus dilakukan secara ketat, terbatas, dan berbasis uji konsekuensi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, Deputi Teknis KPU RI, Eberta Kawima, menyampaikan sosialisasi perubahan Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang menitikberatkan pada penguatan struktur PPID, perlindungan data pribadi, serta penyesuaian tata kelola layanan informasi pasca pemilu. ....

Anggota KPU Provinsi NTT ikuti FGD Pengembangan Kompetensi SDM Learning Management System
Lampung, ntt.kpu.go.id - Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah Kadiv Sosdiklih Parmas & SDM mengikuti Kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPU RI Senin (22/12) di Kantor KPU Provinsi Lampung . FGD tersebut berkaitan dengan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Learning Management System (LMS) Kepemiluan di Indonesia Kepala Pusat PKSDM KPU RI, Dr. Ilham Yamin melaporkan urgensi dan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas sumberaya manusia dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. FGD tersebut dibuka oleh Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI, Dr. Parsadaan Harahap, S.PI, M.Si. Dalam arahannya Parsadaan menyampaikan kegiatan FGD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara pemilu melalui program pelatihan bagi Anggota KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta badan adhoc. Parsadaan juga menekankan perlunya standar kompetensi dan mendorong pelaksanaan sistem pelatihan yang lebih inovatif, akuntabel, dan efisien dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi. KPU RI juga jelas Parsadaan, sedang mengembangkan satu model aplikasi terkait pengembangan pelatihan bagi ASN KPU se-Indonesia melalui aplikasi "Aplikasi Sistem Manajemen Pelatihan (SIMPEL)". Selain itu juga mengembangan Learning Management System (LMS). Selain Parsadaan Harahap, hadir juga anggota KPU RI Dr. Idham Kholik dalam arahannya menekankan pentingnya profesionalisme bagi anggota KPU di semua tingkatan. Dalam perkembangan terkini, menurut Idham, keahlian menjadi sangat penting dalam mengelola kepemiluan. Bahkan tidak lanjut Ilham, menutup kemungkinan penting dipikirkan soal sertifikasi keahlian kepemiluan di masa mendatang agar penyelenggaraan pemilu benar-benar dilakukan secara profesional,dan akuntabel. FGD tersebut menghadirkan dua narasumber Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd, Guruh Muamar Khadafi, S.IP, M.M, Usai materi dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama peserta. ....

Publikasi
Opini

Dari Ruang Publik ke Bilik Suara: Merawat Partisipasi Pemilih di NTT (Bathseba Dapatalu,M.Si.- Kasubag Hukum dan SDM KPU Provinsi NTT) Demokrasi tidak pernah lahir secara tiba-tiba di bilik suara. Ia tumbuh perlahan di ruang-ruang public. Di percakapan warga, di pertukaran gagasan, di kepercayaan yang dirawat antara negara dan rakyatnya. Bilik suara hanyalah muara, sementara partisipasi adalah aliran panjang yang bermula jauh sebelum hari pemungutan suara. Ketika partisipasi direduksi menjadi sekadar persentase kehadiran di TPS, kita sesungguhnya sedang melupakan hakikat demokrasi sebagai proses sosial yang hidup, bernapas, dan terus diuji. Demokrasi tidak pernah lahir dari tabel statistik. Ia tumbuh perlahan dari percakapan yang tak tercatat, dari kegelisahan yang tak disiarkan, dari ruang-ruang sunyi tempat warga saling menyimak dan saling menguji harapan. Demokrasi tidak berawal dari bilik suara. Ia bersemi jauh sebelum hari pemungutan suara, di ruang-ruang tempat warga berkumpul sebagai manusia biasa bukan sebagai pemilih. Di Kota Kupang, demokrasi itu hidup di bangku Taman Nostalgia, di jalur pedestrian Kelapa Lima, di ruang terbuka tempat sore ditukar dengan cerita. Di sanalah kesadaran politik bekerja dalam bentuknya yang paling jujur Di banyak wilayah, termasuk Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur umumnya, demokrasi bekerja dalam lanskap sosial yang khas. Jarak geografis, keterbatasan akses informasi, serta relasi sosial yang kuat berbasis kekerabatan sering kali membentuk cara warga memahami politik. Dalam konteks seperti ini, partisipasi tidak selalu lahir dari bacaan kebijakan atau debat program, melainkan dari obrolan di beranda rumah, diskusi di rumah ibadah, atau percakapan sederhana di pasar dan kebun. Ruang publik lokal menjadi sekolah demokrasi yang paling awal dan paling jujur. Namun ruang publik tidak selalu ramah. Arus disinformasi, hoaks, dan narasi emosional yang menyesatkan kerap menyusup, memanfaatkan kerentanan literasi dan kelelahan sosial. Ketika informasi kehilangan kualitasnya, partisipasi pun terancam berubah menjadi ritual kosong hadir di TPS tanpa benar-benar memahami makna pilihan. Di sinilah demokrasi diuji, bukan pada hari pencoblosan, melainkan jauh sebelumnya, pada kemampuan negara menghadirkan informasi yang jernih dan dapat dipercaya. Bilik suara, dengan segala kesunyiannya, sejatinya adalah ruang yang penuh makna. Di dalamnya, warga membawa seluruh pengalaman sosialnya, informasi yang ia terima, kepercayaan yang ia bangun, serta harapan yang ia titipkan pada masa depan. Jika ruang publik sebelumnya dibiarkan bising dan manipulatif, maka bilik suara akan menjadi tempat keputusan yang rapuh. Sebaliknya, jika ruang publik dirawat dengan kesabaran dan integritas, bilik suara akan melahirkan pilihan yang bermartabat. Ruang Publik sebagai laboratorium demokrasi Di taman ‘Nostalgia’ Kota Kupang sebagai ruang publik misalnya, politik kota hadir tanpa baliho. Anak muda berbincang tentang pekerjaan yang tak kunjung pasti, pedagang kecil merawat keluhnya tentang penertiban, mahasiswa menyusun kritik terhadap kebijakan, keluarga menikmati ruang kota yang dulu terasa jauh. Obrolan ini tampak remeh, namun justru di sanalah opini publik dirajut bukan sebagai hasil propaganda, melainkan sebagai pengalaman bersama. Opini publik, sebagaimana dikatakan para pemikir komunikasi, bukanlah sekadar penjumlahan pendapat individual. Ia adalah proses sosial hasil dari dialog, pertukaran makna, pengaruh simbolik, dan relasi kuasa yang bekerja di ruang publik. Dengan kata lain, demokrasi hidup dari percakapan, bukan dari prosedur semata. Di titik ini, peran Komisi Pemilihan Umum menjadi menarik untuk dibaca ulang. KPU selama ini dikenali sebagai lembaga teknis pengelola tahapan, penjaga jadwal, dan pengaman logistik pemilu. Namun undang-undang menempatkannya lebih dari itu, sebagai pendidik politik warga. Artinya, KPU bukan hanya pengatur mekanisme, tetapi juga penjaga ekosistem demokrasi. Peran KPU dalam konteks ini melampaui tugas administratif. Ia bukan hanya penjaga jadwal, logistik, dan prosedur, tetapi juga penjaga nalar publik. Melalui pendidikan pemilih, sosialisasi berkelanjutan, dan keterbukaan informasi, KPU merawat mata air demokrasi agar tidak kering sebelum sampai ke bilik suara. Kerja ini sering kali sunyi tidak selalu terlihat, tidak selalu dihitung sebagai capaian instan namun justru menentukan kualitas keputusan politik warga. Merawat partisipasi berarti mengakui bahwa memilih bukan akhir dari demokrasi. Ia adalah awal dari relasi panjang antara pemilih dan pemimpin terpilih. Di sinilah partisipasi perlu dimaknai sebagai kesediaan warga untuk terus mengawal, mengkritik, dan menagih janji. Demokrasi yang sehat tidak berhenti pada angka partisipasi, tetapi berlanjut pada keberanian warga untuk tetap terlibat setelah hasil ditetapkan. Di NTT, menurunnya partisipasi pemilih tidak bisa dibaca sebagai kemalasan politik. Data riset evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan partisipasi pemilih, dari 73,89 persen pada Pilkada 2018 menjadi 68,48 persen pada Pilkada 2024 lebih tepat dibaca sebagai jarak. Jarak antara warga dan proses elektoral. Banyak warga peduli pada urusan publik, tetapi tidak merasa cukup dekat dengan dunia politik formal. Partisipasi pemilih tak dapat disederhanakan sebagai gejala apatisme. Banyak warga sesungguhnya menyimpan kepedulian pada urusan publik, namun tidak selalu merasa memiliki ruang yang cukup untuk terlibat dalam diskursus politik. Angka ini bukan sekadar perbandingan statistic, sebuah isyarat bahwa demokrasi masih berjalan, tetapi belum sepenuhnya dihayati sebagai ruang bersama. Jurgen Habermas (2006) dalam bukunya Communication in Media Society menyebut, demokrasi hanya dapat hidup jika public sphere tetap bernapas ruang tempat warga berdialog secara setara tentang urusan bersama. Dalam konteks Kupang, taman kota dan ruang terbuka sesungguhnya adalah ingatan demokrasi yang hidup. Di sana, isu sehari-hari dapat bertransformasi menjadi kesadaran politik. Jika demokrasi tumbuh dari ruang publik, maka kehadiran KPU di ruang-ruang itu bukanlah tambahan, melainkan kebutuhan. Namun kehadiran ini tidak boleh hadir sebagai pengeras suara negara. Ia harus hadir sebagai pendengar sebagai fasilitator dialog, bukan penyampai pengumuman. Pendidikan pemilih, dalam pengertian ini, tidak lagi menjadi proses satu arah. Ia menjelma menjadi percakapan. Demokrasi tidak diajarkan, tetapi dialami. Warga tidak digerakkan, tetapi diajak berpikir bersama. Selama ini, pendidikan pemilih sering direduksi menjadi informasi teknis, tanggal, cara mencoblos, jenis surat suara. Padahal, Habermas menekankan deliberasi ruang bagi warga untuk memahami makna politik dari pilihannya. Tanpa deliberasi, memilih hanya menjadi ritual, dengan deliberasi, memilih menjadi kesadaran. Program-program dialog seperti KoPi Parmas adalah langkah penting, namun demokrasi tidak cukup dirawat di ruang internal. Ia perlu dibawa ke ruang public ke tempat warga berada dalam kesehariannya. Di sanalah demokrasi menjadi cair, inklusif, dan tidak mengintimidasi. Sejalan dengan itu Henri Lefebvre (1968) dalam bukunya The Right to the City mengingatkan bahwa, ruang tidak pernah netral. Ia selalu diproduksi oleh relasi kuasa. Karena itu, kehadiran KPU di ruang publik tidak boleh jatuh pada seremoni yang elitis. Jika ruang publik hanya diisi oleh simbol dan formalitas, maka ia kehilangan daya hidupnya. KPU perlu peka terhadap yang hadir dan yang absen. Pedagang kecil, perempuan, pemilih pemula, dan kelompok marjinal bukan objek sosialisasi, melainkan subjek demokrasi. Mendengar pengalaman mereka, tentang ketidakpercayaan, hambatan akses, atau kelelahan politik adalah kerja demokrasi itu sendiri. Berbagai kajian menunjukkan bahwa partisipasi tumbuh ketika pemilu terasa relevan dengan kehidupan warga. Terutama bagi generasi muda yang lebih akrab dengan ruang publik dan ruang digital dibanding forum formal. Menghadirkan KPU di ruang publik berarti menjumpai pemilih di habitat sosialnya. Ketika warga merasa dilibatkan, memilih tidak lagi lahir dari kewajiban, tetapi dari kepercayaan. Dan kepercayaan (trusth) adalah modal utama demokrasi. Tanpanya, ajakan memilih hanya menjadi gema kosong. Masa depan demokrasi lokal tidak ditentukan oleh siapa yang menang, melainkan oleh sejauh mana warga merasa menjadi bagian dari prosesnya. KPU memiliki peran strategis untuk menjadikan ruang publik sebagai mitra demokrasi bukan sekadar latar kegiatan. Ruang publik yang hidup akan melahirkan warga yang sadar politik. Warga yang sadar politik akan datang ke TPS bukan karena takut absen, tetapi karena merasa bertanggung jawab. Di sanalah demokrasi menemukan maknanya bukan pada angka partisipasi semata, melainkan pada kedalaman keterlibatan warganya. Pada akhirnya, demokrasi adalah kerja merawat. Ia menuntut kesetiaan pada proses, bukan sekadar hasil. Dari ruang publik ke bilik suara, partisipasi warga perlu terus dijaga agar tidak kehilangan ruhnya. Sebab demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana warga sampai pada pilihannya dengan sadar, bebas, dan bertanggung jawab.

Jalan Sunyi Pahlawan Demokrasi Oleh: Baharudin Hamzah Setiap tanggal 10 November, bangsa ini menunduk dalam hening, mengenang mereka yang berkorban untuk kemerdekaan. Namun, di antara gema seremonial dan karangan bunga, ada jenis kepahlawanan lain yang kerap luput dari catatan sejarah. Para penyelenggara pemilu, mereka yang menjadi penjaga setia denyut nadi demokrasi di seluruh pelosok negeri. Mereka bukan pejuang bersenjata, tetapi keberanian mereka diuji dalam medan yang tak kalah berat, medan tanggung jawab dan kejujuran. Mereka membelah lautan menuju pulau-pulau terluar, menyusuri sungai dalam gelap malam, menuruni lembah dan mendaki bukit demi satu tujuan menjaga setiap suara rakyat yang tertitip di dalam kotak suara. Begitu pemilu usai, sorak dan spanduk hilang, berita berganti topik, dan janji-janji mulai terdengar sayup. Ketika janji-janji berganti arah, dan sorak kemenangan mereda, nama-nama mereka perlahan hilang dari ingatan. Negara lupa, politisi seperti kehilangan rasa terima kasih, dan publik beranjak mencari drama politik baru. Padahal, tanpa mereka, demokrasi tak mungkin berdiri tegak, kepercayaan rakyat pada hasil pemilu hanyalah ilusi tanpa pengawal integritas di garis terdepan. Mereka inilah pahlawan demokrasi garda kedelapan republik yang menjaga nadi kepercayaan publik tetap berdetak. Tak banyak yang menoleh kepada mereka yang berpeluh di garis terdepan, yang memastikan setiap suara dihitung dengan benar, dan yang sering menanggung beban moral ketika hasil pemilu dipersoalkan. Padahal, penyelenggara pemilu adalah garda kedelapan republik ini mereka yang menjaga jantung kepercayaan publik, ketika semua yang lain goyah. Integritas mereka adalah pagar terakhir agar demokrasi tak runtuh menjadi sekadar prosedur tanpa ruh. Di tangan mereka, suara rakyat bukan sekadar angka dalam tabel rekapitulasi, melainkan wujud martabat bangsa. Upah bukan problem bagi mereka, dibanding beban dan risiko yang mereka pikul. Mereka bertugas di antara tekanan politik, cuaca yang tak bersahabat, dan situasi sosial yang sering kali tak menentu. Mereka bekerja dalam senyap, sementara sorot lampu panggung demokrasi lebih banyak tertuju pada para kandidat, partai, dan elite politik. Padahal tanpa tangan mereka yang sabar dan jujur, pesta demokrasi hanya akan menjadi sandiwara tanpa makna. Mereka adalah wajah-wajah yang sering tak disebut. Bukan tokoh di layar kaca, bukan pula figur yang dielu-elukan publik. Mereka bekerja di ruang yang sepi di tengah badai logistik, jarak, dan waktu. Mereka menyeberangi lautan, menyusuri sungai, menuruni lembah dan mendaki bukit, hanya untuk memastikan satu hal, bahwa setiap suara rakyat sampai ke kotak suara dan dihitung dengan jujur. Penyelenggara pemilu adalah pengawal demokrasi yang berjalan di jalan sunyi. Mereka menanggung beban berat dalam diam diapit oleh tekanan, ekspektasi publik, dan godaan kekuasaan. Honor mereka tak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka pikul. Tapi mereka tetap bekerja, sebab bagi mereka, menjaga suara rakyat adalah bentuk cinta paling nyata kepada republik ini. Kepahlawanan, dengan demikian, bukan sekadar soal gugur di medan perang. Ia juga berarti bertahan dalam kejujuran, setia pada amanah, dan berani menolak godaan yang mengaburkan nurani. Dalam tubuh para penyelenggara pemilu, kita menemukan bentuk baru dari perjuangan. Perjuangan melawan lupa, melawan tekanan, dan melawan ketidakpedulian bangsa terhadap fondasi demokrasinya sendiri. Maka, di hari Pahlawan ini, marilah kita perluas makna kata “pahlawan.” Mereka tak selalu berdiri di bawah cahaya lampu upacara, tak selalu memiliki nama di prasasti, tapi kerja sunyi mereka membuat republik ini terus berdiri tegak. Pahlawan Demokrasi adalah mereka yang menjaga suara rakyat tetap jernih dari kecurangan. Mereka yang menegakkan keadilan pemilu di tengah godaan pragmatisme. Mereka yang bekerja dengan keyakinan bahwa setiap suara adalah harga diri bangsa. Jika kemerdekaan ditebus dengan darah, maka demokrasi dijaga dengan keringat dan integritas. Dan selagi masih ada mereka yang bersedia menjaga kotak suara dengan hati bersih, maka cita-cita para pahlawan 1945 masih terus berdenyut di bumi Indonesia. Kepahlawanan masa kini bukan lagi soal mengangkat senjata, tetapi soal keberanian untuk tetap jujur ketika sistem menggoda untuk curang, soal keteguhan menolak tekanan, dan kesetiaanuntuk menunaikan amanah dalam kesunyian. Di tengah badai pragmatisme dan derasnya disinformasi, kerja mereka adalah tembok terakhir agar demokrasi tak berubah menjadi sekadar ritual lima tahunan tanpa makna. Hari Pahlawan semestinya juga menjadi hari refleksi bagi demokrasi kita. Bahwa ada mereka yang berpeluh tanpa sorotan, yang rela mengorbankan waktu, keluarga, bahkan nyawa, demi menjaga marwah pemilu. Mereka bukan hanya pelaksana teknis, tetapi penjaga moral bangsa. Selama masih ada yang bersedia menjaga kotak suara dengan integritas, selama masih ada yang percaya bahwa setiap suara adalah sakral, selama itu pula cita-cita para pahlawan kemerdekaan tetap hidup di setiap TPS, di setiap surat suara, dan di setiap langkah sunyi para pengawal demokrasi. Dalam bukunya Mereka yang Terlupakan (2020), Baharudin Hamzah menyebut penyelenggara pemilu sebagai “para pengawal demokrasi yang berjalan di jalan sunyi.” Mereka adalah benteng moral yang tak hanya menjalankan prosedur, tetapi menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.Di sinilah relevan pandangan Robert A. Dahl dalam Polyarchy: Participation and Opposition (1971), bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika dijaga oleh institusi yang menjamin partisipasi dan kontestasi secara adil. Penyelenggara pemilu adalah manifestasi konkret dari gagasan itu mereka adalah pilar institusional yang memastikan demokrasi bukan sekadar retorika politik, melainkan sistem yang hidup dan dipercaya rakyat. Sementara Robert D. Putnam dalam Making Democracy Work (1993) menekankan bahwa, keberhasilan demokrasi bergantung pada modal sosial pada jaringan kepercayaan, norma, dan kerja sama warga.Penyelenggara pemilu adalah simpul penting dalam modal sosial itu. Mereka menanamkan kepercayaan dengan kerja yang jujur dan transparan, membangun legitimasi melalui keteladanan, serta memperkuat kohesi sosial di tengah kompetisi politik yang sering kali memecah belah. Tanpa mereka, suara rakyat tak akan sampai, tanpa mereka, keadilan elektoral hanyalah mitos. Mereka inilah pahlawan demokrasi masa kini bukan karena sorak penghargaan, tetapi karena kesetiaan mereka menjaga nurani republik. Di bawah panas terik dan hujan badai, mereka memastikan bahwa setiap surat suara sekecil apa pun nilainya sampai dan dihitung. Mereka menjaga martabat bangsa dalam bentuk paling sederhana namun paling bermakna integritas. Kepahlawanan hari ini bukan hanya tentang keberanian di medan perang, tetapi tentang keberanian untuk tetap jujur di tengah sistem yang mudah tergoda untuk curang, tentang keteguhan hati untuk melayani negara tanpa pamrih. Dalam kerja senyap para penyelenggara pemilu, kita belajar bahwa demokrasi tidak hanya berdiri di atas hukum, tetapi juga di atas keikhlasan manusia. Hari Pahlawan seharusnya menjadi momen reflektif bagi bangsa ini untuk mengingat bahwa demokrasi bukan hadiah, melainkan perjuangan terus-menerus. Dan dalam perjuangan itu, para penyelenggara pemilu adalah garda terakhir penjaga kotak suara sekaligus penjaga kepercayaan rakyat terhadap negara. Selama masih ada mereka yang rela membelah lautan demi suara rakyat, selama masih ada yang memilih jujur meski tak disorot kamera, selama itu pula cita-cita para pahlawan 1945 tetap berdenyut dalam setiap tinta di jari, dalam setiap suara yang dihitung dengan hati. Honor mereka tak sepadan dengan beban moral yang dipikul. Tugas mereka berat, menegakkan aturan, melawan tekanan, menjaga kejujuran, di tengah godaan dan keterbatasan. Namun mereka tetap bertahan, sebab bagi mereka, bekerja untuk demokrasi bukan sekadar profesi, melainkan pengabdian. Mereka bukan selebritas politik. Tapi mereka pembuat keputusan besar. Mereka adalah penjaga legitimasi republik, menyeberangi lautan, menuruni lembah, menyusuri sungai, mendaki bukit, demi memastikan setiap suara tiba dan dihitung dengan benar. Tanggung jawab mereka besar. Mereka bekerja di bawah tekanan waktu, sorotan publik, dan kadang di tengah badai politik. Namun mereka bertahan, sebab bagi mereka demokrasi bukan sekadar prosedur, melainkan iman sipil yang harus dijaga. Sebab demokrasi bukanlah karya satu malam, melainkan proses panjang yang dijaga dengan kejujuran, kesetiaan, dan keberanian moral. Mereka dipuji oleh yang menang, dan dimaki oleh yang kalah. Padahal merekalah yang memastikan keadilan tetap berdiri di antara dua sisi kepentingan. Begitu besar jasa mereka bagi mekarnya demokrasi negeri ini, tetapi sedikit saja tergelincir dalam kebijakan, publik seakan lupa semua pengorbanan itu. Seolah melupakan seluruh keberhasilan dan pengabdian para penyelenggara pemilu. Mereka yang dengan dedikasi tanpa pamrih menjaga tegaknya demokrasi negeri ini. Semua pengabdian seakan lenyap ditelan ingatan publik. Padahal di balik setiap pemilu yang berjalan damai, ada ribuan langkah penyelenggara yang bekerja dalam diam menjaga demokrasi agar tetap berdenyut di nadi republik ini. *) Anggota KPU Provinsi NTT/Alumni Ilmu Administrasi FISIP UNDANA

Kearifan Lokal Menuju Demokrasi Berkeadaban: Ikhtiar Menjaga Demokrasi Tetap Berakar Catatan dari Indonesian Association for Public Administration (IAPA) 2025 Annual Conference & Congress, Undana Kupang Oleh: Baharudin Hamzah Di penghujung Oktober 2025, Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menjadi ruang perjumpaan gagasan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (Undana) menjadi tuan rumah perhelatan besar Indonesian Association for Public Administration (IAPA) 2025. Konferensi dan kongres tahun ini tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, melainkan ruang perenungan kolektif tentang ke mana arah ilmu administrasi publik Indonesia hendak dibawa. Tema yang diangkat “Indigenous Public Administration: Bridging Tradition, Innovation, and Governance for a World-Class Public Sector”, mengandung pesan mendasar bahwa tata kelola pemerintahan masa depan tidak boleh tercerabut dari akar budaya yang menjadi sumber identitas, sekaligus peta moral bagi perjalanan bangsa. Di tengah maraknya jargon digitalisasi pemerintahan, transformasi birokrasi, dan dorongan menuju pemerintahan berkelas dunia, konferensi ini menghadirkan kesadaran baru bahwa modernitas tidak boleh menjadi jalan sunyi yang meninggalkan nilai. Kecanggihan sistem tidak boleh mengalahkan kemanusiaan. Teknologi bukan pengganti kearifan, melainkan pelayan bagi nilai. Negara bisa membangun pusat data dan kecerdasan buatan, tetapi tetap membutuhkan ruang batin tempat nilai-nilai diolah, ditimbang, dan dibenarkan. Modernitas yang kehilangan kesadaran budaya adalah modernitas yang rapuh. Karena itu, membahas administrasi publik tidak hanya soal prosedur, struktur, dan efisiensi, tetapi juga persoalan etika, makna, dan roh sosial yang menghidupinya. Di hadapan para akademisi dan praktisi kebijakan, kita diajak untuk menundukkan kepala sejenak dan mendengar kembali suara tanah tempat kita berpijak. Administrasi publik modern tidak boleh menjadi bangunan besar tanpa fondasi kultural. Administrasi harus bertumpu pada nilai yang tumbuh dari sejarah, adat, dan spiritualitas masyarakat. Sebab negara, sebelum menjadi sistem hukum, adalah rumah batin dan hasil kesepakatan nurani kolektif. Itulah sebabnya konferensi ini membuka jalan bagi kesadaran baru, bahwa administrasi publik harus kembali ke manusianya, kepada jiwa yang memberi arah, bukan semata mesin yang memberi bentuk. Seorang pemikir, Aloysius Liliweri, mengingatkan bahwa ilmu administrasi publik hanya akan bernyawa jika ia bersentuhan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti komunikasi, antropologi, filsafat, bahkan seni. Tanpa sentuhan itu, birokrasi akan kering, dingin, dan jauh dari manusia yang dilayaninya. Hal ini mengajak kita membaca birokrasi bukan hanya sebagai sistem, tetapi juga sebagai bahasa bagaiaman cara petugas menyapa, cara kantor dirancang, cara simbol negara dipasang, bagaimana ruang pelayanan dibuka dan ditutup, kesemuanya adalah tanda yang menyampaikan pesan tentang kekuasaan, empati, atau jarak sosial. Pendekatan semiotika mengajarkan bahwa di balik setiap tanda tersimpan makna yang membentuk persepsi publik tentang negara. Ketika seorang ASN tersenyum, negara sedang tersenyum. Saat prosedur dipermudah, martabat warga dimuliakan. Sebaliknya, ketika birokrasi membentengkan diri dengan dingin, negara sedang menciptakan jarak yang menggerus legitimasi. Di titik ini, kita tiba pada realitas sederhana namun penuh daya bahwa kearifan lokal bukan romantika masa lalu, tetapi sumber cahaya bagi masa depan tata kelola publik. Di Nusa Tenggara Timur, tanah yang kaya budaya dan spiritualitas, hal ini terlihat jelas. Inovasi dan digitalisasi diperlukan, tetapi keduanya menemukan ruh-nya ketika berjalan bersama cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan, kebersamaan, dan martabat manusia. Di banyak kampung di Flores, Sumba, Timor, hingga Lembata dan Adonara, kehidupan publik diikat bukan hanya oleh norma formal, tetapi oleh nilai adat yang mengedepankan musyawarah, penghormatan pada tetua, dan rasa saling menjaga sebagai keluarga besar. Nilai-nilai itu memberi arah moral bagi hubungan antara warga dan pemimpin; antara mereka yang memegang mandat dan mereka yang memberi mandat. Dalam konteks ini, tradisi toto kenito di Desa Dawata, Adonara Timur, memberikan pelajaran mendalam. Ritual penandaan dahi dengan minyak oleh kepala suku sebagai bentuk pengakuan kewargaan bukan sekadar upacara adat. Ia adalah bahasa legitimasi; tanda bahwa seseorang diakui, diterima, dan menjadi bagian dari komunitas moral. Tradisi ini membuktikan bahwa jauh sebelum negara memperkenalkan sistem data kependudukan dan daftar pemilih, masyarakat telah memiliki mekanisme pengakuan sosial yang hidup. Ketika tanda itu diletakkan di dahi seseorang, masyarakat berkata “engkau bukan sekadar dihitung, tapi diterima; engkau bukan hanya dilihat, tetapi diakui”. Betapa menarik bahwa negara modern kemudian mengenal praktik serupa dalam pemilu, tinta di jari setelah mencoblos adalah penanda kehadiran sekaligus pengakuan kewargaan. Dua dunia, adat dan negara, bertemu dalam simbol yang sama bahwa manusia harus diakui keberadaannya sebelum diminta berpartisipasi. Dengan kata lain, demokrasi modern menemukan gemanya dalam kearifan tradisional. Demokrasi bukan hanya prosedur, tetapi pengakuan hakiki atas martabat setiap manusia. Sayangnya, dalam praktik empiris, demokrasi kita kerap terjebak dalam ruang formal seperti daftar pemilih, logistik, bilik suara, rekapitulasi, dan mekanisme teknis yang detil. Semua itu penting, tetapi demokrasi kehilangan daya geraknya ketika hanya menjadi ritual administratif. Demokrasi yang sehat mensyaratkan lebih dari kesempurnaan prosedur. Indonesia sering dipuji sebagai demokrasi besar. Tetapi demokrasi yang besar belum tentu demokrasi yang berjiwa. Di banyak daerah, pemilu terasa seperti “acara negara” yang ditentukan dari atas, dilaksanakan dengan disiplin teknokratis, tetapi kurang menyapa ruang batin masyarakat. Padahal, demokrasi sejati tumbuh di tanah yang hidup dengan nilai, bukan hanya di meja yang penuh formulir. Di NTT, kita masih menjumpai praktik sosial menarik menjelang pemungutan suara. Tokoh adat dan warga memanggil kembali mereka yang merantau agar pulang memilih di kampung halaman. Bagi mereka, pemimpin yang layak dipilih adalah mereka yang lahir dari tanah yang sama, merasakan denyut kehidupan masyarakatnya. Ini bukan bentuk eksklusivitas; ini kesaksian tentang pentingnya kedekatan moral pemimpin dengan rakyatnya. Demokrasi bagi mereka bukan angka dalam kotak, tetapi relasi batin: kepemimpinan yang tumbuh dari tanah dan kembali mengabdi pada tanah. Pada tataran teori, pandangan seperti ini sejalan dengan pemikiran H. George Frederickson tentang social equity, bahwa keadilan sosial tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari bagaimana warga diperlakukan. Ia mengingatkan kita bahwa administrasi publik harus melampaui logika netralitas, menuju etika keberpihakan pada kemanusiaan. Sementara Gerald E. Caiden menegaskan bahwa reformasi pemerintahan sejati adalah humanizing governance yang menjadikan kekuasaan sarana memuliakan manusia, bukan mempersulit hidupnya. Pesan-pesan ini bertemu dalam ruang budaya Indonesia: bahwa tata kelola publik sejati harus menyentuh rasa sebelum mengatur prosedur. Dari perspektif itu, demokrasi Indonesia menemukan bentuk idealnya bukan hanya di ruang sidang parlemen, tetapi di balai adat; bukan hanya di regulasi tertulis, tetapi dalam musyawarah keluarga besar; bukan hanya di sistem informasi pemilu, tetapi dalam nilai gotong royong. Demokrasi yang terlalu teknokratis akan kehilangan kepekaan. Demokrasi yang hanya menghitung suara tanpa mendengar suara batin rakyat akan menjadi demokrasi yang lelah. Di sinilah pelajaran penting IAPA tahun ini, teknologi harus bersujud pada nilai. Inovasi harus berjalan bersama belas kasih. Bongkahan data pemilih tidak pernah mampu menggantikan tatap mata warga di kampung, perangkat lunak tidak akan pernah mengalahkan kebijaksanaan seorang tetua adat yang paham kapan harus bicara dan kapan harus diam. Demokrasi adalah jembatan antara negara dan budaya. Demokrasi membutuhkan struktur, namun tidak kehilangan jiwa. Ia memerlukan sistem, tetapi tetap dipandu nilai. Ketika negara hadir di ruang adat, ia harus mengulurkan tangan, bukan membawa jarak. Ketika budaya bertemu modernitas, keduanya harus saling menyapa, bukan saling menggusur. Inilah jalan menuju demokrasi berkeadaban, demokrasi yang tumbuh dari kebiasaan, dari percakapan, dari rasa percaya. Demokrasi yang tidak hanya mematuhi konstitusi, tetapi juga menghormati kearifan nenek moyang. Di akhir forum, terasa jelas bahwa konferensi ini bukan sekadar pertemuan, akan tetapi menjadi panggilan agar administrasi publik Indonesia berjalan di jalan tengah yang bijak. Sehingga dapat membangun digital government tanpa meninggalkan rumah budaya kita, agar negara hadir bukan sebagai mesin, tetapi sebagai sahabat hidup dan penjaga martabat manusia. Dari Kupang, dari ruang akademik Undana, dari perjalanan pemikiran yang menyentuh tanah dan langit sekaligus, sebuah kesadaran lahir bahwa demokrasi Indonesia harus dibangun bukan hanya dengan undang-undang, tetapi dengan kearifan; bukan hanya dengan sistem, tetapi dengan jiwa; bukan hanya dengan suara, tetapi dengan kesadaran. Negara hanya akan kuat bila ia tidak melupakan rumah budaya tempat ia berasal. Demokrasi hanya akan subur bila ia dipelihara oleh rasa saling percaya, kejujuran, dan kesediaan untuk mendengar. Dalam tradisi Adonara, tanda di dahi adalah pengakuan. Dalam negara modern, tinta di jari adalah pengakuan. Dalam kehidupan bersama, pengakuan manusia atas manusia lain adalah pijakan tertinggi dari peradaban. Dengan demikian, tugas kita adalah menjaga agar negara tidak hanya menghitung suara, tetapi juga menghitung martabat, agar pemilu tidak hanya memilih pemimpin, tetapi meneguhkan kesadaran kolektif bahwa kita adalah satu bangsa yang berjalan bersama di jalan yang sama. Administrasi publik yang berkeadaban adalah administrasi yang memahami manusia bukan sebagai data, tetapi sebagai jiwa. Dan demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang kembali ke rumah awalnya, rumah di mana budaya, nilai, dan kemanusiaan tumbuh bersama. *) Anggota KPU Provinsi NTT/Alumni Ilmu Administrasi FISIP UNDANA

Sumpah Pemuda, Janji Merawat Demokrasi Negeri Oleh Baharudin Hamzah Setiap kali tanggal 28 Oktober tiba, Sumpah Pemuda kembali menggema sebagai ingatan kolektif bangsa yakni satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Namun, sumpah itu tidak boleh membeku dalam arsip sejarah, sekadar jadi poster peringatan tahunan. Sumpah itu harus menjadi janji moral yang menuntut perawatan terhadap demokrasi yang kini digempur derasnya disrupsi digital, banjir informasi, dan erosi nalar publik. Demokrasi Indonesia hari ini menghadapi paradoks yang subtil tapi nyata. Di satu sisi, ruang digital membuka kanal partisipasi politik yang belum pernah sebesar ini. Dari ujung jari, siapa pun kini dapat menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan, bahkan menggerakkan solidaritas sosial lintas batas. Namun di sisi lain, ruang digital itu juga menjadi medan rapuh bagi demokrasi, tempat algoritma membungkus opini, tempat polarisasi menyusup dalam bentuk yang nyaris tak kasat mata, dan tempat banalitas merayap pelan-pelan menggerus nalar kritis warga. Seperti diingatkan Robert A. Dahl, demokrasi hanya akan hidup jika ada “partisipasi efektif” dan “kesetaraan suara”. Tapi dalam masyarakat yang dikepung sensasi, kecepatan, dan emosi digital, rasionalitas publik sering kali tumbang. Demokrasi tidak hanya diuji oleh institusinya, tetapi oleh kualitas nalar warganya. Jauh sebelum demokrasi menjadi sistem modern, Plato dalam The Republic telah memberi peringatan bahwa kebebasan tanpa kebajikan akan melahirkan tirani, tirani yang bukan datang dari penguasa, melainkan dari rakyat yang berhenti berpikir. Kini, peringatan itu menjelma dalam realitas, kebebasan berekspresi yang tak ditopang tanggung jawab etis mudah berubah menjadi ladang hoaks, ujaran kebencian, dan delegitimasi kepercayaan publik. Demokrasi tak mati oleh kudeta, melainkan oleh ketidakpedulian warganya sendiri. Yang sesungguhnya terancam bukan hanya sistem elektoral, melainkan roh deliberatif yang menopang kehidupan bernegara. Ketika publik kehilangan ruang untuk berpikir jernih, ketika percakapan politik lebih banyak dipandu amarah daripada akal sehat, maka demokrasi berubah dari rumah bersama menjadi arena perpecahan. Demokrasi kehilangan substansinya ketika hanya menjadi ritual elektoral tanpa ruh etis dan kesadaran kolektif. Karena itu, tugas generasi muda bukan hanya menjadi pemilih, tetapi menjadi guardian of the civic mind. Karena itulah, pendidikan pemilih dan pendidikan politik tidak boleh dipandang remeh sekadar urusan teknis menjelang pemilu. Pendidikan pemilih sejatinya membentuk warga deliberatif, mereka yang memahami makna suara, mampu memilah informasi, dan sadar tanggung jawab setelah hari pemungutan suara usai. Demokrasi bukan ritus lima tahunan, tetapi proses panjang menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional. Dalam konteks inilah, program “KPU Mengajar” yang diusung KPU Provinsi NTT menemukan makna praksisnya. Program ini menjadi gerakan untuk menanamkan kesadaran kritis, bahwa memilih adalah tindakan moral, bukan sekadar ritual. Dalam kerangka konseptual Dahl, program ini memperkuat dua pilar demokrasi yakni enlightened understanding dan control of the agenda, pemahaman tercerahkan dan kemampuan menentukan arah isu publik. Landasan filosofisnya dapat ditelusuri jauh ke pemikiran Plato, pendidikan adalah inti dari keadilan politik. Tanpa pendidikan, rakyat mudah digiring oleh retorika dan kepentingan sempit. “KPU Mengajar” dengan cara itu menjadi philosophical praxis, cara paling sederhana untuk merawat jiwa demokrasi berdasarkan nalar publik. Di tengah riuh rendah disrupsi digital, program ini mengembalikan makna politik pada tempat asalnya sebagai perjuangan bersama demi kebaikan publik (the common good), bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan. Pendidikan pemilih berkelanjutan adalah investasi jangka panjang demokrasi untuk menyiapkan generasi yang tidak mudah dibeli oleh pragmatisme murahan, tetapi berpikir dengan nalar kritis dan etika publik. Demokrasi tidak tumbuh dari sensasi digital, tetapi dari warga yang tercerahkan dan berani berpikir jernih. Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesadaran kolektif untuk bersatu melawan penjajahan. Kini, sumpah itu menuntut tafsir baru berupa janji generasi penerus untuk merawat demokrasi agar tak dikerdilkan menjadi kontestasi elitis. Ia harus dihidupkan kembali sebagai cita-cita bersama dalam menciptakan republik yang adil, berakal sehat, dan berperikemanusiaan. Karena itu, bila Sumpah Pemuda 1928 menjadi momentum kebangkitan kesadaran kebangsaan, maka hari ini kita memerlukan “Sumpah Demokrasi” sebagai janji kolektif untuk menjaga nalar publik, melawan disinformasi, menolak politik uang, dan mengembalikan kepercayaan warga terhadap demokrasi. Merawat demokrasi berarti mengubah sumpah menjadi tindakan, bukan hanya mencoblos, tetapi juga mengawasi, bukan hanya bersuara, tetapi juga mendengar, bukan hanya menuntut, tetapi juga bertanggung jawab. Dari partisipasi yang sadar dan berkelanjutan itulah demokrasi akan terus bersemi. *) Anggota KPU Povinsi NTT/Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM

Menanti Revisi UU: Pemilu Sebagai Panggung Kedaulatan Rakyat Oleh Jemris Fointuna Pemilu adalah momentum di mana seluruh rakyat dikonsolidasikan ke dalam satu ruang kebangsaan yang utuh, melampaui segmentasi sosial dan partisi golongan. Dalam logika demokrasi, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai pernyataan (deklaratif) bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Posisi rakyat tidak boleh direduksi menjadi simbolik semata, melainkan harus hadir nyata sebagai pusat pengambilan keputusan. Bertentangan dengan kehendak rakyat sama dengan meruntuhkan kepercayaan publik (public trust) dan pada akhirnya membuka ruang bagi public recall di masa depan. Dengan kata lain, Pemilu adalah bentuk nyata dari pactum unionis (perjanjian kesatuan) dan pactum subjectionis (perjanjian penyerahan diri), di mana rakyat bersepakat membentuk tatanan politik sekaligus menyerahkan mandatnya pada penyelenggara negara. Dalam konteks pengesahan partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu, rakyat berperan sebagai juru kunci utama. Aturan mewajibkan setiap Parpol memiliki basis konstituen di berbagai tingkatan wilayah serta membuktikan militansinya melalui kepemilikan KTA. Prinsip kesukarelaan (voluntarysm) yang menjadi dasar keanggotaan partai menunjukkan ruang kebebasan rakyat untuk bergabung, tetapi begitu menjadi anggota, seseorang terikat pada statuta partai. Banyak partai akhirnya gagal memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu karena tidak mampu membuktikan legitimasi rakyat yang menjadi fondasi keberadaannya. Ketika tahapan pencalonan dimulai, ruang ekspresi rakyat semakin terbuka lebar. Hampir semua Parpol mengakomodasi beragam latar belakang calon, mulai dari politisi, akademisi, pengusaha, aktivis, buruh, ibu rumah tangga, budayawan, artis, hingga petani dan pekerja informal. Dengan modal KTA, peluang mencalonkan diri terbuka. Fenomena ini memperlihatkan Pemilu sebagai arena sosial yang menyatukan berbagai aspirasi rakyat. Namun, di balik keterbukaan itu, ada paradoks: keterlibatan rakyat yang tampak luas bisa saja hanya menjadi ornamen prosedural, di mana rakyat dijadikan obyek mobilisasi politik, bukan subyek yang sungguh berdaulat. Strategi Parpol dalam menyatukan kekuatan rakyat pada tahap pencalonan kerap memberi efek kejut pada hasil pemungutan suara. Banyak calon rela meninggalkan profesi mapan demi masuk ke gelanggang politik, seakan-akan jabatan hasil Pemilu adalah segalanya. Padahal jabatan itu hanya berlangsung lima tahun, dengan segala risiko hukum dan politik yang menyertainya. Pola ini memperlihatkan daya hipnosis Pemilu, tetapi sekaligus menyimpan bahaya ketika rakyat hanya diposisikan sebagai alat legitimasi formal tanpa dijamin ruang kontrol berkelanjutan. Di sisi lain, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) memikul tanggung jawab besar. Mereka mengkonsolidasikan hak rakyat menjadi daftar pemilih yang sah melalui kriteria ketat seperti usia, status pernikahan, kepemilikan identitas, dan ketidakikutsertaan sebagai aparat negara. Setiap deviasi dalam proses ini berpotensi menghilangkan hak rakyat untuk memilih, yang bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi dan sila keempat Pancasila. Ketika data pemilih kacau, kedaulatan rakyat terguncang, dan Pemilu berisiko kehilangan legitimasinya. Ekspektasi pasangan calon, Parpol serta calon anggota DPD terhadap kinerja penyelenggara Pemilu begitu besar, dengan menegaskan narasi “Suara Rakyat Suara Tuhan.” Narasi ini mengandung makna mendalam bahwa setiap suara harus dihargai sebagai mandat ilahi yang melahirkan legitimasi politik. Pada tahapan ini, posisi rakyat khususnya pemilih ditempatkan sebagai King and Queen, karena merekalah mandataris kedaulatan yang mewarisi hak untuk ikut memilih. Sedikit saja terjadi deviasi berpotensi menghilangkan hak pilih rakyat. Konsekuensi logis dari kelalaian mengelola data pemilih mengakibatkan hilangnya public trust. Dalam konteks yang lebih luas, penyelenggara Pemilu dianggap melakukan contempt of election berupa pelanggaran Konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila, pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kampanye kemudian menjadi ruang interaksi intensif antara rakyat dan peserta Pemilu. Secara ideal, kampanye menjadi wadah simbiosis mutualisme, tempat aspirasi rakyat bertemu dengan visi dan program politik. Namun, bila kampanye hanya dijalankan sebagai instrumen untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, maka rakyat kembali direduksi menjadi objek persuasi. Pada titik ini, ada bahaya bahwa Pemilu lebih berfungsi sebagai panggung pencitraan ketimbang arena pemberdayaan rakyat. Sistem proporsional terbuka memang menegaskan prinsip one man, one vote, one value. Nilai suara seorang buruh setara dengan nilai suara seorang presiden. Kesetaraan inilah yang membuat rakyat merasa terhormat, karena suaranya tidak kalah berharga dengan suara elite. Namun, sejarah Pemilu Indonesia menunjukkan partisipasi rakyat tidak pernah mencapai 100 persen. Angka partisipasi tertinggi justru terjadi pada Pemilu 1971 di era otoritarian dengan 96,6 persen, namun ironisnya ini adalah masa ketika demokrasi masih bersifat semu. Angka tinggi itu bukan lahir dari partisipasi sejati, melainkan dari kontrol negara yang kuat. Inilah gambaran paling jelas dari pseudo demokrasi, partisipasi rakyat hanya tinggi di atas kertas, tetapi nihil kedaulatan substantif. Kini, setelah DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-5 menyetujui 67 RUU prioritas, termasuk RUU Pemilu dan RUU Pemilihan Kepala Daerah, publik kembali mempertanyakan posisi rakyat. Apakah setelah kodifikasi UU ini rakyat tetap diposisikan sebagai pemegang kedaulatan, ataukah justru hanya sebagai penggembira demokrasi? Apabila revisi undang-undang lebih diarahkan pada penekanan teknokrasi prosedural seraya mengurangi ruang partisipasi substantif rakyat, maka yang akan lahir bukanlah demokrasi yang menghidupi rakyat, melainkan sebentuk pseudo demokrasi yang hanya menampilkan kulit luarnya. Demokrasi kehilangan vitalitasnya ketika kedaulatan rakyat dipersempit menjadi sekadar legitimasi formal, tanpa jaminan ruang artikulasi aspirasi yang otentik. Jika ditelisik lebih jauh pada substansi pasal-pasal yang berpotensi diubah, problematika segera tampak. Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) selama ini hanya berfungsi mengonsolidasikan dominasi partai besar dan menutup kemungkinan lahirnya alternatif politik baru. Konsekuensinya adalah rakyat kehilangan keberagaman pilihan, padahal pluralitas politik merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 yang menghapus threshold tersebut karenanya dapat dibaca sebagai koreksi historis. Namun, momentum ini masih menyimpan risiko. Bila revisi undang-undang justru kembali memasukkan mekanisme pembatasan lain yang pada hakikatnya menyerupai threshold, maka esensi putusan MK akan tereduksi, dan kedaulatan rakyat kembali dipersempit. Begitu pula wacana kembalinya sistem proporsional tertutup yang menempatkan daftar calon sepenuhnya dalam kendali elite partai. Langkah ini sesungguhnya menegasikan esensi kedaulatan rakyat, karena pemilih tidak lagi memiliki keleluasaan menentukan secara langsung siapa yang akan mewakili kepentingannya di parlemen. Lebih jauh lagi, apabila verifikasi partai politik diperketat tanpa disertai mekanisme yang inklusif, maka lanskap politik yang tercipta cenderung semakin oligarkis. Partai-partai kecil yang kerap menjadi kanal artikulasi bagi aspirasi alternatif rakyat akan kesulitan tampil dalam kontestasi. Padahal, keberadaan mereka justru penting sebagai penyeimbang hegemoni partai besar serta sebagai indikator sejauh mana demokrasi mampu menampung keragaman suara warga. Dengan demikian, revisi yang tidak sensitif terhadap dimensi kedaulatan rakyat berpotensi menggeser demokrasi Indonesia dari ranah substantif menuju prosedural semata. Semua ini berpotensi memundurkan kualitas demokrasi kita, menjadikannya hanya sebagai etalase prosedural yang indah dilihat, tetapi kosong makna. Bahaya pseudo demokrasi terletak pada kenyataan bahwa wajah luar tetap menampilkan mekanisme demokratis: Pemilu berlangsung, rakyat datang ke TPS, hasil diumumkan. Namun, di balik ritual itu, substansi kedaulatan rakyat perlahan terkikis. Demokrasi hanya menjadi pesta lima tahunan, sementara ruang kontrol rakyat di antara periode itu tertutup rapat. Rakyat sekadar dipanggil hadir sebagai legitimasi formal, tetapi suara kritisnya dibatasi, bahkan cenderung dibungkam. Oleh karena itu, revisi UU Pemilu bukan hanya soal harmonisasi regulasi, melainkan juga soal menjaga substansi kedaulatan rakyat. Penantian publik terhadap UU baru sejatinya adalah penantian terhadap jawaban, apakah bangsa ini setia pada amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, atau justru tergelincir kembali ke masa lalu ketika demokrasi hanya formalitas. Jika arah revisi menjauh dari rakyat, maka Pemilu Indonesia akan jatuh ke dalam pseudo demokrasi, hanya meriah di permukaan, tetapi kehilangan ruh kedaulatan di dalamnya.