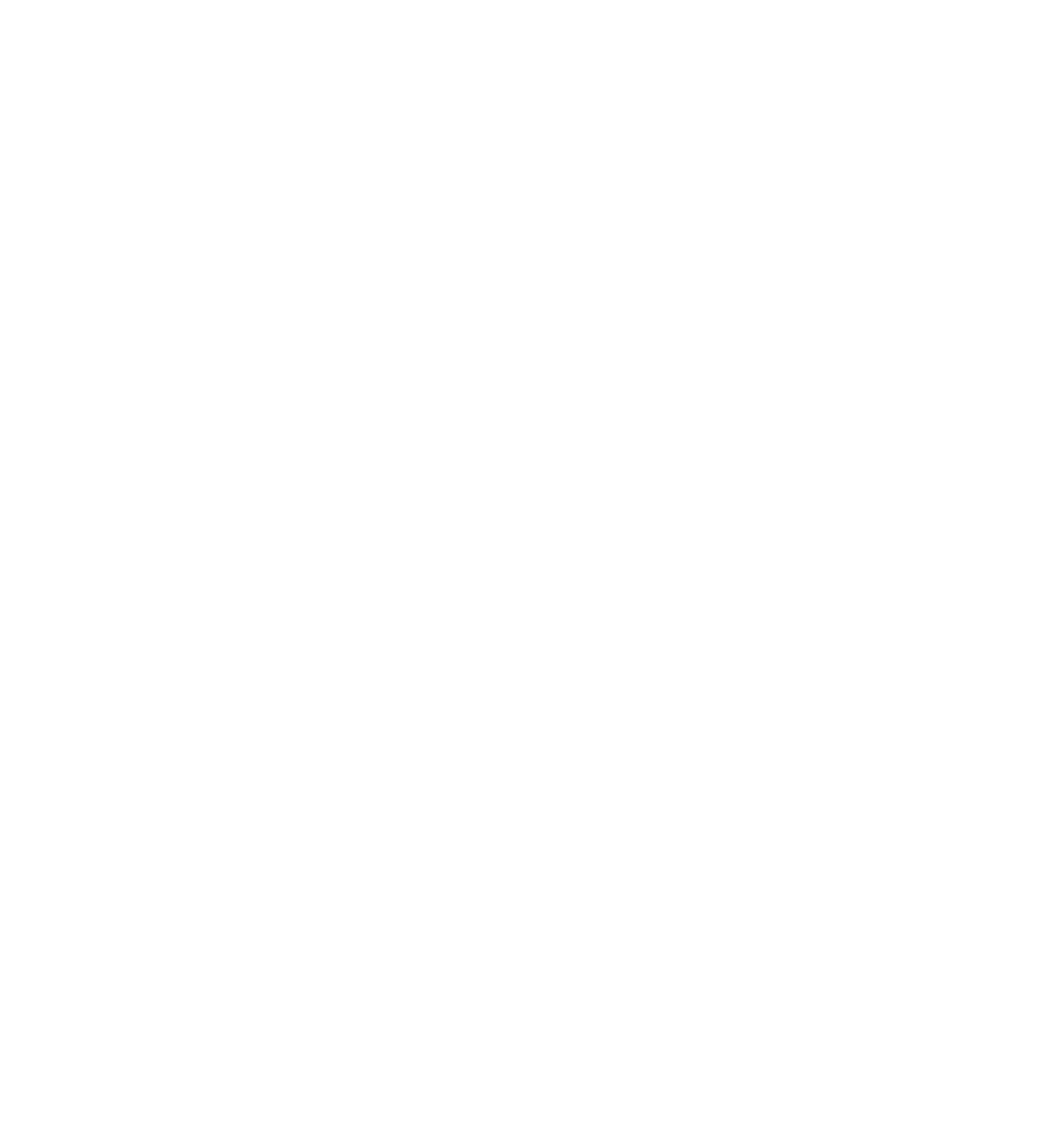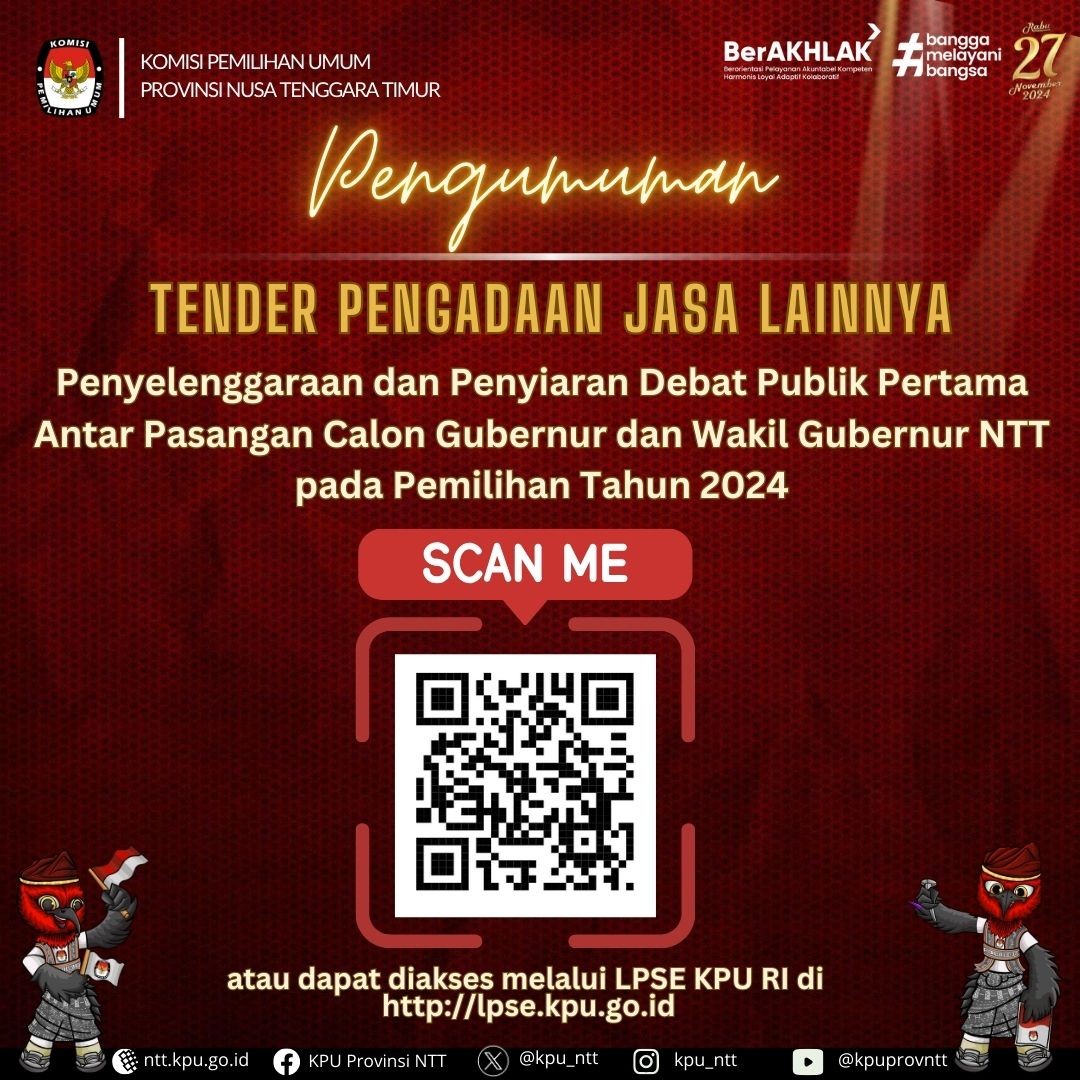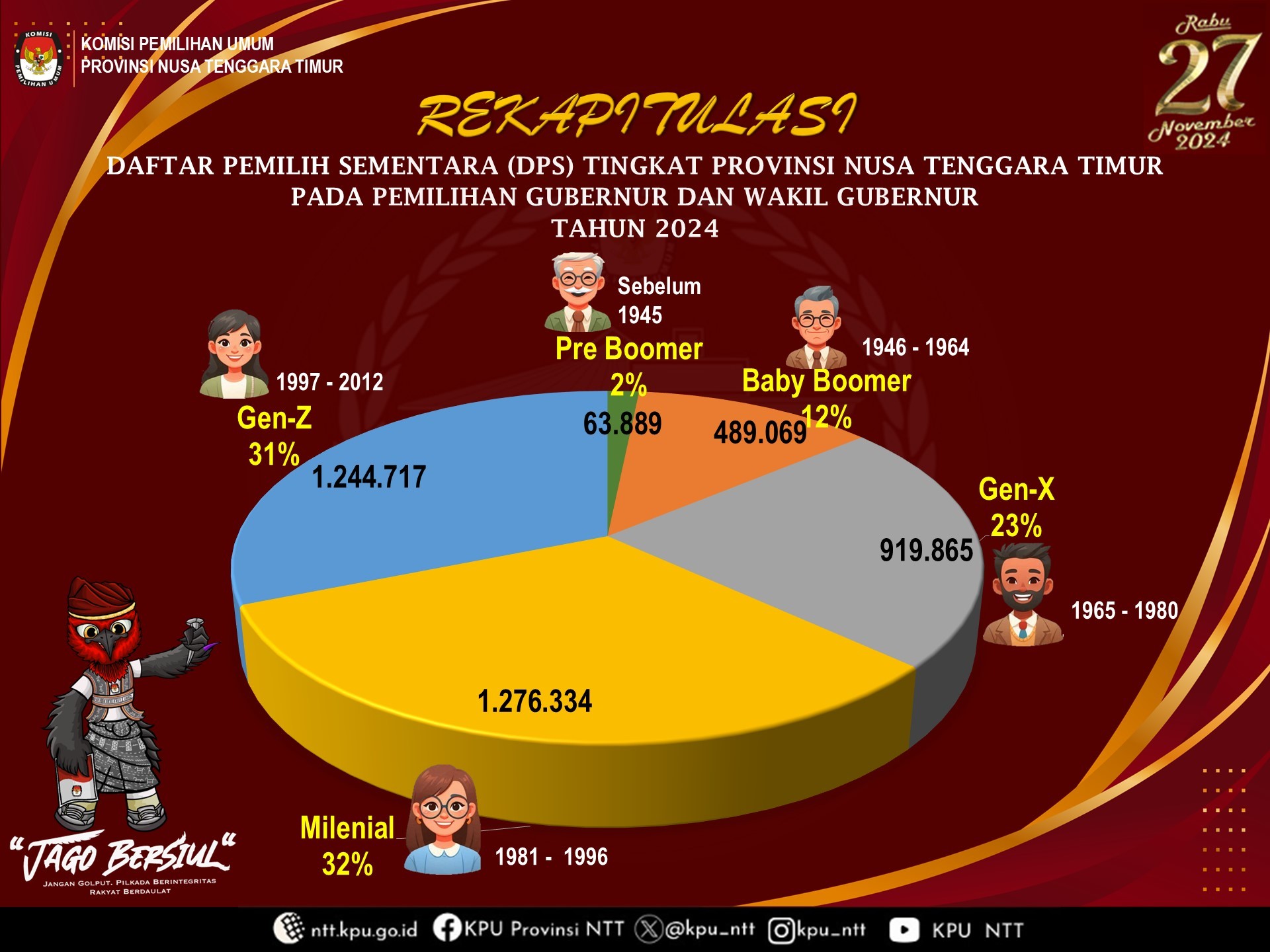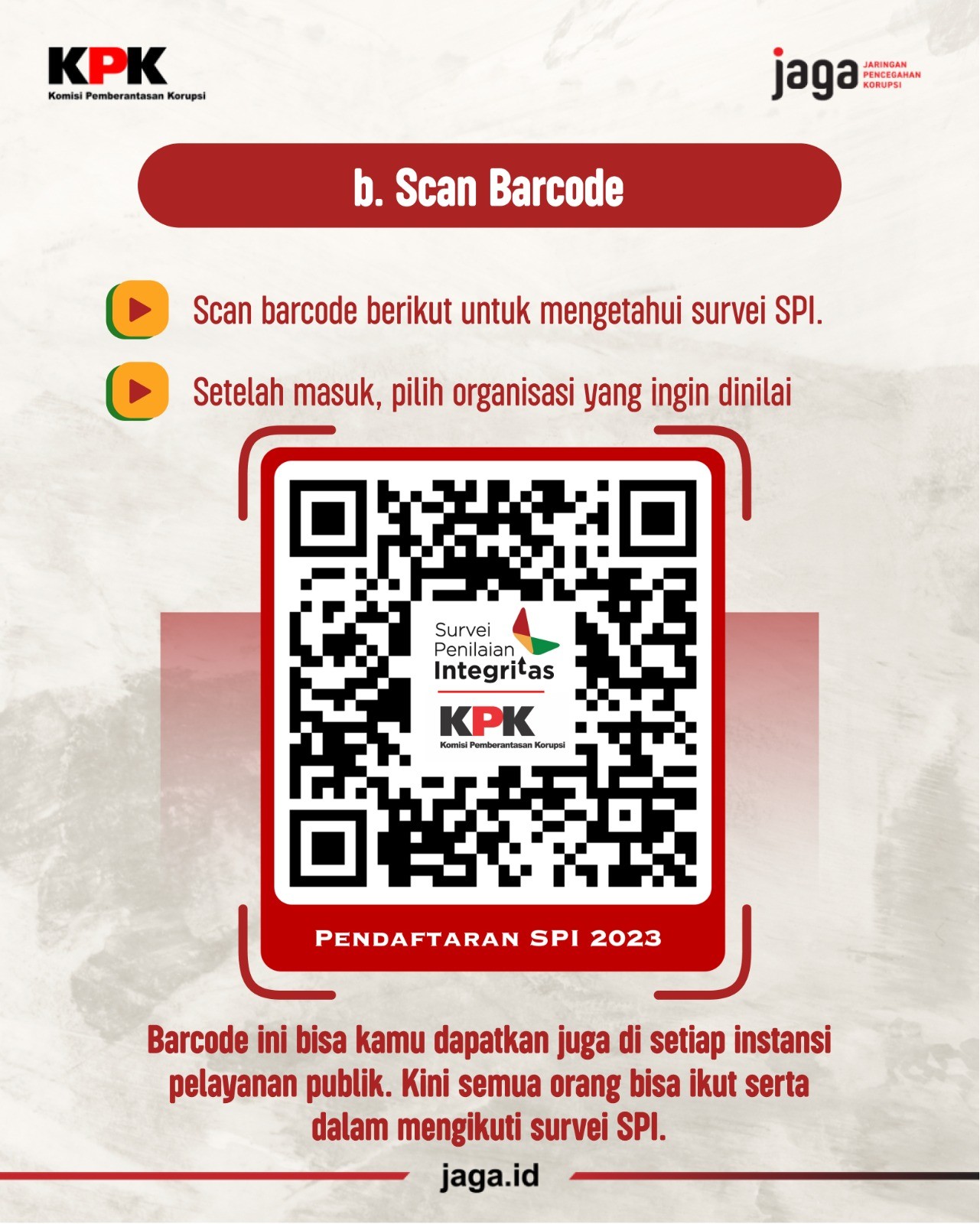KPU NTT Ikuti Pembekalan Penggunaan Aplikasi SIMPEL dari KPU RI
Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIMPEL) pada Selasa, (18/11). Kegiatan ini menghadirkan Anna Marisi, Penata Kelola Pemilu Ahli Madya KPU RI, sebagai narasumber yang menyampaikan materi secara luring di Aula KPU NTT dan diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-NTT melalui Zoom Meeting. Dalam pemaparannya, Anna Marisi menjelaskan peran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKSDM) KPU RI dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi ASN KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan bagian dari penguatan profesionalisme penyelenggara pemilu, terutama dalam menghadapi dinamika tahapan Pemilu dan Pemilihan yang semakin kompleks. Anna juga menguraikan dasar hukum pengembangan kompetensi ASN, merujuk pada Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018, yang memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi melalui berbagai skema pembelajaran. Aplikasi SIMPEL, menurutnya, berfungsi sebagai platform nasional untuk mencatat, memantau, dan mengelola rekam jejak pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi. Lebih jauh, Anna memberikan penjelasan teknis mengenai tahapan yang harus dilakukan oleh ASN melalui akun SIMPEL, mulai dari proses login, pembaruan data profil, hingga penguploadan sertifikat pelatihan. Ia menekankan bahwa setiap ASN harus memastikan rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan dan analisis kebutuhan organisasi. Bukti pelatihan seperti sertifikat, daftar hadir, dan laporan kegiatan juga harus diunggah secara tepat agar dapat diverifikasi oleh admin satker. Anna juga memaparkan langkah-langkah pelaporan jam pelatihan (Jam Pelajaran/JP) melalui SIMPEL, termasuk cara mengunggah dokumen pendukung dan proses validasi oleh unit SDM. Ia mengingatkan bahwa sesuai ketentuan, ASN KPU wajib memenuhi minimal 20 JP pelatihan per tahun, sedangkan PPPK memiliki batas maksimal 24 JP. Pemenuhan kompetensi ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja ASN sekaligus mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU. Kegiatan pembekalan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman satker dalam mengoptimalkan Aplikasi SIMPEL sebagai instrumen manajemen SDM yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kapasitas ini juga menjadi langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas. Kegiatan diikuti oleh Plh. Sekretaris KPU NTT Andrew S. N. Kette, Plh. Kabag Perencanaan, Data dan Informasi Aryans T. Fanu, Kasubbag Keuangan Peiter G. Nappoe, serta staf sekretariat KPU Provinsi NTT. Dari KPU Kabupaten/Kota se-NTT, peserta mengikuti pembekalan secara daring melalui Zoom Meeting. ....

KPU NTT Ikuti Bimtek Pengolahan, Analisis, dan Visualisasi Data yang Diselenggarakan KPU RI
Jakarta, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan, Analisis, dan Visualisasi Data yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada 16-17 November 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Morrissey, Jakarta, dan diikuti oleh jajaran KPU Provinsi dari seluruh Indonesia. KPU Provinsi NTT menghadirkan dua peserta, yakni Plt. Sekretaris KPU NTT yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Melanie Sari Willa Hege, serta Operator Data, Tati Haryati Husein. Keikutsertaan keduanya menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan data kepemiluan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) KOMPAS, yang menyampaikan materi mendalam mengenai metodologi analisis data serta pendekatan visualisasi informasi yang efektif, akurat, dan mudah dipahami publik. Para peserta mendapatkan wawasan mengenai bagaimana data kepemiluan dapat diolah dan ditampilkan secara lebih informatif untuk mendukung transparansi publik. Selain sesi materi, peserta juga mengikuti praktik langsung yang mencakup pengolahan data berbasis digital, teknik analisis kuantitatif, penyusunan insight data, penggunaan Google Looker Studio, serta pembuatan dashboard interaktif yang relevan untuk kebutuhan pelaporan dan pengambilan keputusan di lingkungan KPU. Melalui bimtek ini, KPU Provinsi NTT diharapkan semakin siap dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data, memperkuat keterbukaan informasi publik, serta mendukung kelancaran dan akuntabilitas tahapan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang. Kegiatan ditutup oleh Kepala Pusat Data dan Informasi KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, yang dalam arahannya berharap seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh serta menularkannya kepada satuan kerja KPU Kabupaten/Kota. Ia menegaskan pentingnya penyajian data yang valid dan terpercaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPU. ....

KPU NTT Gelar Apel Pagi, Baharudin Tekankan Kreativitas dan Inovasi di Setiap Divisi
Kupang, ntt.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Apel Pagi pada Senin (17/11) di halaman Kantor KPU NTT. Bertindak sebagai pembina apel yaitu Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah, yang membawahi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Apel pagi dihadiri oleh Ketua KPU NTT Jemris Fointuna, Anggota KPU NTT Lodowyk Fredrik, serta Plh. Sekretaris KPU NTT Andrew S. N. Kette, bersama para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh staf sekretariat KPU NTT. Dalam amanatnya, Baharudin Hamzah menyampaikan pesan penting mengenai perlunya setiap divisi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, terutama dalam periode non-tahapan. Ia menekankan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya bekerja pada saat tahapan berlangsung, tetapi juga harus memanfaatkan masa jeda untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperkaya program kerja. “Kreativitas dan inovasi harus menjadi budaya kerja kita. Setiap divisi memiliki ruang untuk mengembangkan ide, memperbaiki pola kerja, dan menghasilkan terobosan yang memberi nilai tambah bagi lembaga,” ujar Baharudin. Ia juga mendorong agar setiap divisi proaktif melihat peluang pengembangan kegiatan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, literasi kepemiluan, serta koordinasi antar divisi. Menurutnya, penguatan kreatifitas di internal lembaga akan berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pada periode mendatang. Selain terkait kinerja kelembagaan, Baharudin juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Mengingat ritme pekerjaan penyelenggara pemilu yang sering kali tinggi dan menuntut kesiapan ekstra, ia meminta seluruh jajaran untuk menerapkan pola hidup sehat dan memperhatikan kondisi tubuh. “Kesehatan adalah modal utama kita. Ritme kerja di penyelenggara pemilu cukup dinamis. Karena itu, mari kita saling mengingatkan dan menjaga kesehatan agar tetap bugar serta siap menjalankan tugas,” tambahnya. Lebih lanjut, Baharudin menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan seluruh pegawai yang tetap konsisten mengikuti apel rutin dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Ia berharap semangat kebersamaan dalam apel pagi dapat terus memperkuat budaya kerja positif di lingkungan KPU Provinsi NTT. Apel pagi ditutup dengan ajakan untuk menjaga sinergi antar divisi dan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung tata kelola lembaga yang profesional, adaptif, dan berintegritas. ....

KPU NTT Ikuti Seminar Nasional Desain Manajemen Penyelenggaraan Pemilu yang Lebih Inklusif dan Akuntabel
Jakarta, ntt.kpu.go.id — Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna bersama Anggota KPU Provinsi NTT Elyaser Lomi Rihi mengikuti Seminar Nasional Desain Manajemen Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Lebih Inklusif, Partisipatif, dan Akuntabel, yang dirangkaikan dengan Diseminasi Hasil Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Tematik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia dan berlangsung pada 13-15 November 2025 di Jakarta. Seminar nasional tersebut dibuka oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu di seluruh tingkat harus bekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan hasil kerja yang memiliki kepastian hukum, akuntabilitas, serta integritas yang kuat. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus profesional agar penyelenggaraan pemilu terhindar dari persoalan hukum maupun etik. Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik menyampaikan pentingnya penguasaan pengetahuan demokrasi elektoral bagi jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurutnya, penyelenggara pemilu wajib memahami substansi teknis seperti sistem pemilu, kampanye dan dana kampanye, mekanisme pencalonan, verifikasi partai politik, serta seluruh rangkaian tahapan pemilu lainnya. Idham juga menyinggung dinamika perubahan Undang-Undang Pemilu, sambil menegaskan bahwa KPU berada pada posisi sebagai pelaksana undang-undang. Namun demikian, jika diminta memberi masukan secara resmi, KPU selalu siap memberikan rekomendasi demi penyempurnaan pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Seminar nasional ini menghadirkan beragam narasumber dari kalangan akademisi, peneliti, hingga pejabat pemerintah, yang menyampaikan perspektif komprehensif terkait penyelenggaraan pemilu. Materi yang disampaikan mencakup refleksi dan proyeksi verifikasi partai politik, transparansi serta akuntabilitas dana kampanye, tantangan kompleksitas pemilu di Indonesia, penataan daerah pemilihan, aspek pemungutan dan penghitungan suara, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, hingga gagasan reformasi kampanye menuju Pemilu 2029 yang lebih adaptif dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemutakhiran pengetahuan serta gambaran menyeluruh mengenai isu-isu strategis kepemiluan nasional. KPU Provinsi NTT berharap hasil seminar dapat menjadi referensi penting dalam memperkuat kapasitas internal, meningkatkan kualitas perencanaan teknis, serta memastikan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang semakin berintegritas di masa mendatang. ....

KPU NTT Ikuti Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Setjen KPU RI
Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia pada Jumat (14/11) di ruang RPP KPU NTT. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Utama Setjen KPU, Jakarta, serta melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus menindaklanjuti hasil Penilaian SPI Tahun 2024 di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota. Dari KPU Provinsi NTT, kegiatan ini diikuti oleh Plt. Sekretaris KPU NTT Melanie Sari Willa Hege, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Carolus F. Dengi, Kasubbag Keuangan Peiter G. Nappoe, serta staf pelaksana yang menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam kegiatan ini, Irwil 3 KPU RI Ferry Syahminan menekankan pentingnya keteraturan dalam setiap proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Penyampaian materi juga menyoroti langkah-langkah penguatan pengawasan internal serta upaya memastikan kesesuaian proses keuangan dengan standar akuntabilitas penyelenggara negara. KPU RI berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi dan kesiapan seluruh satuan kerja dalam menghadapi pemeriksaan maupun proses pelaporan keuangan berbasis regulasi nasional dan standar audit yang berlaku. Dengan mengikuti sosialisasi ini, KPU Provinsi NTT berkomitmen memperkuat kualitas tata kelola keuangan lembaga secara konsisten, profesional, dan transparan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan berintegritas. ....

KPU Provinsi NTT menggelar kegiatan Penguatan Kesekretariatan bagi KPU Kabupaten Sumba Tengah
Kupang, ntt.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Penguatan Kesekretariatan bagi KPU Kabupaten Sumba Tengah pada Kamis (13/11), secara daring bertempat di Ruang RPP KPU Provinsi NTT. Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT, Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik, Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah, Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik, serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan dimulai pukul 10.00 WITA dan dibuka oleh Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk diskusi dan sesi berbagi pengalaman untuk memperkuat tata kelola kesekretariatan, khususnya terkait kepegawaian, keuangan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam arahannya, Melanie Sari Willa Hege, Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT yang juga menjabat sebagai Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting sebagai bentuk mitigasi risiko kelembagaan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, disiplin kepegawaian, ketepatan dalam pertanggungjawaban LPJ keuangan, distribusi tugas yang jelas, serta pelaksanaan program yang terukur. Sementara itu, Sekretaris KPU Sumba Tengah, Umbu Tamu, menjelaskan bahwa KPU Sumba Tengah telah menjalankan ketentuan disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Pembagian tugas telah dilaksanakan secara proporsional, termasuk dalam pemberdayaan CPNS. Program pendidikan pemilih seperti KPU Mengajar dan kegiatan Coktas juga berjalan dengan baik melalui optimalisasi penggunaan anggaran. Selanjutnya, Carolus Dengi, selaku Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi NTT, memberikan penegasan mengenai alur pengelolaan keuangan. Kegiatan ditutup pada pukul 12.00 WITA dengan penegasan bahwa penguatan kesekretariatan merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola satuan kerja (satker) berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. ....

Publikasi
Opini

Kearifan Lokal Menuju Demokrasi Berkeadaban: Ikhtiar Menjaga Demokrasi Tetap Berakar Catatan dari Indonesian Association for Public Administration (IAPA) 2025 Annual Conference & Congress, Undana Kupang Oleh: Baharudin Hamzah Di penghujung Oktober 2025, Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menjadi ruang perjumpaan gagasan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (Undana) menjadi tuan rumah perhelatan besar Indonesian Association for Public Administration (IAPA) 2025. Konferensi dan kongres tahun ini tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, melainkan ruang perenungan kolektif tentang ke mana arah ilmu administrasi publik Indonesia hendak dibawa. Tema yang diangkat “Indigenous Public Administration: Bridging Tradition, Innovation, and Governance for a World-Class Public Sector”, mengandung pesan mendasar bahwa tata kelola pemerintahan masa depan tidak boleh tercerabut dari akar budaya yang menjadi sumber identitas, sekaligus peta moral bagi perjalanan bangsa. Di tengah maraknya jargon digitalisasi pemerintahan, transformasi birokrasi, dan dorongan menuju pemerintahan berkelas dunia, konferensi ini menghadirkan kesadaran baru bahwa modernitas tidak boleh menjadi jalan sunyi yang meninggalkan nilai. Kecanggihan sistem tidak boleh mengalahkan kemanusiaan. Teknologi bukan pengganti kearifan, melainkan pelayan bagi nilai. Negara bisa membangun pusat data dan kecerdasan buatan, tetapi tetap membutuhkan ruang batin tempat nilai-nilai diolah, ditimbang, dan dibenarkan. Modernitas yang kehilangan kesadaran budaya adalah modernitas yang rapuh. Karena itu, membahas administrasi publik tidak hanya soal prosedur, struktur, dan efisiensi, tetapi juga persoalan etika, makna, dan roh sosial yang menghidupinya. Di hadapan para akademisi dan praktisi kebijakan, kita diajak untuk menundukkan kepala sejenak dan mendengar kembali suara tanah tempat kita berpijak. Administrasi publik modern tidak boleh menjadi bangunan besar tanpa fondasi kultural. Administrasi harus bertumpu pada nilai yang tumbuh dari sejarah, adat, dan spiritualitas masyarakat. Sebab negara, sebelum menjadi sistem hukum, adalah rumah batin dan hasil kesepakatan nurani kolektif. Itulah sebabnya konferensi ini membuka jalan bagi kesadaran baru, bahwa administrasi publik harus kembali ke manusianya, kepada jiwa yang memberi arah, bukan semata mesin yang memberi bentuk. Seorang pemikir, Aloysius Liliweri, mengingatkan bahwa ilmu administrasi publik hanya akan bernyawa jika ia bersentuhan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti komunikasi, antropologi, filsafat, bahkan seni. Tanpa sentuhan itu, birokrasi akan kering, dingin, dan jauh dari manusia yang dilayaninya. Hal ini mengajak kita membaca birokrasi bukan hanya sebagai sistem, tetapi juga sebagai bahasa bagaiaman cara petugas menyapa, cara kantor dirancang, cara simbol negara dipasang, bagaimana ruang pelayanan dibuka dan ditutup, kesemuanya adalah tanda yang menyampaikan pesan tentang kekuasaan, empati, atau jarak sosial. Pendekatan semiotika mengajarkan bahwa di balik setiap tanda tersimpan makna yang membentuk persepsi publik tentang negara. Ketika seorang ASN tersenyum, negara sedang tersenyum. Saat prosedur dipermudah, martabat warga dimuliakan. Sebaliknya, ketika birokrasi membentengkan diri dengan dingin, negara sedang menciptakan jarak yang menggerus legitimasi. Di titik ini, kita tiba pada realitas sederhana namun penuh daya bahwa kearifan lokal bukan romantika masa lalu, tetapi sumber cahaya bagi masa depan tata kelola publik. Di Nusa Tenggara Timur, tanah yang kaya budaya dan spiritualitas, hal ini terlihat jelas. Inovasi dan digitalisasi diperlukan, tetapi keduanya menemukan ruh-nya ketika berjalan bersama cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan, kebersamaan, dan martabat manusia. Di banyak kampung di Flores, Sumba, Timor, hingga Lembata dan Adonara, kehidupan publik diikat bukan hanya oleh norma formal, tetapi oleh nilai adat yang mengedepankan musyawarah, penghormatan pada tetua, dan rasa saling menjaga sebagai keluarga besar. Nilai-nilai itu memberi arah moral bagi hubungan antara warga dan pemimpin; antara mereka yang memegang mandat dan mereka yang memberi mandat. Dalam konteks ini, tradisi toto kenito di Desa Dawata, Adonara Timur, memberikan pelajaran mendalam. Ritual penandaan dahi dengan minyak oleh kepala suku sebagai bentuk pengakuan kewargaan bukan sekadar upacara adat. Ia adalah bahasa legitimasi; tanda bahwa seseorang diakui, diterima, dan menjadi bagian dari komunitas moral. Tradisi ini membuktikan bahwa jauh sebelum negara memperkenalkan sistem data kependudukan dan daftar pemilih, masyarakat telah memiliki mekanisme pengakuan sosial yang hidup. Ketika tanda itu diletakkan di dahi seseorang, masyarakat berkata “engkau bukan sekadar dihitung, tapi diterima; engkau bukan hanya dilihat, tetapi diakui”. Betapa menarik bahwa negara modern kemudian mengenal praktik serupa dalam pemilu, tinta di jari setelah mencoblos adalah penanda kehadiran sekaligus pengakuan kewargaan. Dua dunia, adat dan negara, bertemu dalam simbol yang sama bahwa manusia harus diakui keberadaannya sebelum diminta berpartisipasi. Dengan kata lain, demokrasi modern menemukan gemanya dalam kearifan tradisional. Demokrasi bukan hanya prosedur, tetapi pengakuan hakiki atas martabat setiap manusia. Sayangnya, dalam praktik empiris, demokrasi kita kerap terjebak dalam ruang formal seperti daftar pemilih, logistik, bilik suara, rekapitulasi, dan mekanisme teknis yang detil. Semua itu penting, tetapi demokrasi kehilangan daya geraknya ketika hanya menjadi ritual administratif. Demokrasi yang sehat mensyaratkan lebih dari kesempurnaan prosedur. Indonesia sering dipuji sebagai demokrasi besar. Tetapi demokrasi yang besar belum tentu demokrasi yang berjiwa. Di banyak daerah, pemilu terasa seperti “acara negara” yang ditentukan dari atas, dilaksanakan dengan disiplin teknokratis, tetapi kurang menyapa ruang batin masyarakat. Padahal, demokrasi sejati tumbuh di tanah yang hidup dengan nilai, bukan hanya di meja yang penuh formulir. Di NTT, kita masih menjumpai praktik sosial menarik menjelang pemungutan suara. Tokoh adat dan warga memanggil kembali mereka yang merantau agar pulang memilih di kampung halaman. Bagi mereka, pemimpin yang layak dipilih adalah mereka yang lahir dari tanah yang sama, merasakan denyut kehidupan masyarakatnya. Ini bukan bentuk eksklusivitas; ini kesaksian tentang pentingnya kedekatan moral pemimpin dengan rakyatnya. Demokrasi bagi mereka bukan angka dalam kotak, tetapi relasi batin: kepemimpinan yang tumbuh dari tanah dan kembali mengabdi pada tanah. Pada tataran teori, pandangan seperti ini sejalan dengan pemikiran H. George Frederickson tentang social equity, bahwa keadilan sosial tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari bagaimana warga diperlakukan. Ia mengingatkan kita bahwa administrasi publik harus melampaui logika netralitas, menuju etika keberpihakan pada kemanusiaan. Sementara Gerald E. Caiden menegaskan bahwa reformasi pemerintahan sejati adalah humanizing governance yang menjadikan kekuasaan sarana memuliakan manusia, bukan mempersulit hidupnya. Pesan-pesan ini bertemu dalam ruang budaya Indonesia: bahwa tata kelola publik sejati harus menyentuh rasa sebelum mengatur prosedur. Dari perspektif itu, demokrasi Indonesia menemukan bentuk idealnya bukan hanya di ruang sidang parlemen, tetapi di balai adat; bukan hanya di regulasi tertulis, tetapi dalam musyawarah keluarga besar; bukan hanya di sistem informasi pemilu, tetapi dalam nilai gotong royong. Demokrasi yang terlalu teknokratis akan kehilangan kepekaan. Demokrasi yang hanya menghitung suara tanpa mendengar suara batin rakyat akan menjadi demokrasi yang lelah. Di sinilah pelajaran penting IAPA tahun ini, teknologi harus bersujud pada nilai. Inovasi harus berjalan bersama belas kasih. Bongkahan data pemilih tidak pernah mampu menggantikan tatap mata warga di kampung, perangkat lunak tidak akan pernah mengalahkan kebijaksanaan seorang tetua adat yang paham kapan harus bicara dan kapan harus diam. Demokrasi adalah jembatan antara negara dan budaya. Demokrasi membutuhkan struktur, namun tidak kehilangan jiwa. Ia memerlukan sistem, tetapi tetap dipandu nilai. Ketika negara hadir di ruang adat, ia harus mengulurkan tangan, bukan membawa jarak. Ketika budaya bertemu modernitas, keduanya harus saling menyapa, bukan saling menggusur. Inilah jalan menuju demokrasi berkeadaban, demokrasi yang tumbuh dari kebiasaan, dari percakapan, dari rasa percaya. Demokrasi yang tidak hanya mematuhi konstitusi, tetapi juga menghormati kearifan nenek moyang. Di akhir forum, terasa jelas bahwa konferensi ini bukan sekadar pertemuan, akan tetapi menjadi panggilan agar administrasi publik Indonesia berjalan di jalan tengah yang bijak. Sehingga dapat membangun digital government tanpa meninggalkan rumah budaya kita, agar negara hadir bukan sebagai mesin, tetapi sebagai sahabat hidup dan penjaga martabat manusia. Dari Kupang, dari ruang akademik Undana, dari perjalanan pemikiran yang menyentuh tanah dan langit sekaligus, sebuah kesadaran lahir bahwa demokrasi Indonesia harus dibangun bukan hanya dengan undang-undang, tetapi dengan kearifan; bukan hanya dengan sistem, tetapi dengan jiwa; bukan hanya dengan suara, tetapi dengan kesadaran. Negara hanya akan kuat bila ia tidak melupakan rumah budaya tempat ia berasal. Demokrasi hanya akan subur bila ia dipelihara oleh rasa saling percaya, kejujuran, dan kesediaan untuk mendengar. Dalam tradisi Adonara, tanda di dahi adalah pengakuan. Dalam negara modern, tinta di jari adalah pengakuan. Dalam kehidupan bersama, pengakuan manusia atas manusia lain adalah pijakan tertinggi dari peradaban. Dengan demikian, tugas kita adalah menjaga agar negara tidak hanya menghitung suara, tetapi juga menghitung martabat, agar pemilu tidak hanya memilih pemimpin, tetapi meneguhkan kesadaran kolektif bahwa kita adalah satu bangsa yang berjalan bersama di jalan yang sama. Administrasi publik yang berkeadaban adalah administrasi yang memahami manusia bukan sebagai data, tetapi sebagai jiwa. Dan demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang kembali ke rumah awalnya, rumah di mana budaya, nilai, dan kemanusiaan tumbuh bersama. *) Anggota KPU Provinsi NTT/Alumni Ilmu Administrasi FISIP UNDANA

Sumpah Pemuda, Janji Merawat Demokrasi Negeri Oleh Baharudin Hamzah Setiap kali tanggal 28 Oktober tiba, Sumpah Pemuda kembali menggema sebagai ingatan kolektif bangsa yakni satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Namun, sumpah itu tidak boleh membeku dalam arsip sejarah, sekadar jadi poster peringatan tahunan. Sumpah itu harus menjadi janji moral yang menuntut perawatan terhadap demokrasi yang kini digempur derasnya disrupsi digital, banjir informasi, dan erosi nalar publik. Demokrasi Indonesia hari ini menghadapi paradoks yang subtil tapi nyata. Di satu sisi, ruang digital membuka kanal partisipasi politik yang belum pernah sebesar ini. Dari ujung jari, siapa pun kini dapat menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan, bahkan menggerakkan solidaritas sosial lintas batas. Namun di sisi lain, ruang digital itu juga menjadi medan rapuh bagi demokrasi, tempat algoritma membungkus opini, tempat polarisasi menyusup dalam bentuk yang nyaris tak kasat mata, dan tempat banalitas merayap pelan-pelan menggerus nalar kritis warga. Seperti diingatkan Robert A. Dahl, demokrasi hanya akan hidup jika ada “partisipasi efektif” dan “kesetaraan suara”. Tapi dalam masyarakat yang dikepung sensasi, kecepatan, dan emosi digital, rasionalitas publik sering kali tumbang. Demokrasi tidak hanya diuji oleh institusinya, tetapi oleh kualitas nalar warganya. Jauh sebelum demokrasi menjadi sistem modern, Plato dalam The Republic telah memberi peringatan bahwa kebebasan tanpa kebajikan akan melahirkan tirani, tirani yang bukan datang dari penguasa, melainkan dari rakyat yang berhenti berpikir. Kini, peringatan itu menjelma dalam realitas, kebebasan berekspresi yang tak ditopang tanggung jawab etis mudah berubah menjadi ladang hoaks, ujaran kebencian, dan delegitimasi kepercayaan publik. Demokrasi tak mati oleh kudeta, melainkan oleh ketidakpedulian warganya sendiri. Yang sesungguhnya terancam bukan hanya sistem elektoral, melainkan roh deliberatif yang menopang kehidupan bernegara. Ketika publik kehilangan ruang untuk berpikir jernih, ketika percakapan politik lebih banyak dipandu amarah daripada akal sehat, maka demokrasi berubah dari rumah bersama menjadi arena perpecahan. Demokrasi kehilangan substansinya ketika hanya menjadi ritual elektoral tanpa ruh etis dan kesadaran kolektif. Karena itu, tugas generasi muda bukan hanya menjadi pemilih, tetapi menjadi guardian of the civic mind. Karena itulah, pendidikan pemilih dan pendidikan politik tidak boleh dipandang remeh sekadar urusan teknis menjelang pemilu. Pendidikan pemilih sejatinya membentuk warga deliberatif, mereka yang memahami makna suara, mampu memilah informasi, dan sadar tanggung jawab setelah hari pemungutan suara usai. Demokrasi bukan ritus lima tahunan, tetapi proses panjang menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional. Dalam konteks inilah, program “KPU Mengajar” yang diusung KPU Provinsi NTT menemukan makna praksisnya. Program ini menjadi gerakan untuk menanamkan kesadaran kritis, bahwa memilih adalah tindakan moral, bukan sekadar ritual. Dalam kerangka konseptual Dahl, program ini memperkuat dua pilar demokrasi yakni enlightened understanding dan control of the agenda, pemahaman tercerahkan dan kemampuan menentukan arah isu publik. Landasan filosofisnya dapat ditelusuri jauh ke pemikiran Plato, pendidikan adalah inti dari keadilan politik. Tanpa pendidikan, rakyat mudah digiring oleh retorika dan kepentingan sempit. “KPU Mengajar” dengan cara itu menjadi philosophical praxis, cara paling sederhana untuk merawat jiwa demokrasi berdasarkan nalar publik. Di tengah riuh rendah disrupsi digital, program ini mengembalikan makna politik pada tempat asalnya sebagai perjuangan bersama demi kebaikan publik (the common good), bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan. Pendidikan pemilih berkelanjutan adalah investasi jangka panjang demokrasi untuk menyiapkan generasi yang tidak mudah dibeli oleh pragmatisme murahan, tetapi berpikir dengan nalar kritis dan etika publik. Demokrasi tidak tumbuh dari sensasi digital, tetapi dari warga yang tercerahkan dan berani berpikir jernih. Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesadaran kolektif untuk bersatu melawan penjajahan. Kini, sumpah itu menuntut tafsir baru berupa janji generasi penerus untuk merawat demokrasi agar tak dikerdilkan menjadi kontestasi elitis. Ia harus dihidupkan kembali sebagai cita-cita bersama dalam menciptakan republik yang adil, berakal sehat, dan berperikemanusiaan. Karena itu, bila Sumpah Pemuda 1928 menjadi momentum kebangkitan kesadaran kebangsaan, maka hari ini kita memerlukan “Sumpah Demokrasi” sebagai janji kolektif untuk menjaga nalar publik, melawan disinformasi, menolak politik uang, dan mengembalikan kepercayaan warga terhadap demokrasi. Merawat demokrasi berarti mengubah sumpah menjadi tindakan, bukan hanya mencoblos, tetapi juga mengawasi, bukan hanya bersuara, tetapi juga mendengar, bukan hanya menuntut, tetapi juga bertanggung jawab. Dari partisipasi yang sadar dan berkelanjutan itulah demokrasi akan terus bersemi. *) Anggota KPU Povinsi NTT/Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM

Menanti Revisi UU: Pemilu Sebagai Panggung Kedaulatan Rakyat Oleh Jemris Fointuna Pemilu adalah momentum di mana seluruh rakyat dikonsolidasikan ke dalam satu ruang kebangsaan yang utuh, melampaui segmentasi sosial dan partisi golongan. Dalam logika demokrasi, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai pernyataan (deklaratif) bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Posisi rakyat tidak boleh direduksi menjadi simbolik semata, melainkan harus hadir nyata sebagai pusat pengambilan keputusan. Bertentangan dengan kehendak rakyat sama dengan meruntuhkan kepercayaan publik (public trust) dan pada akhirnya membuka ruang bagi public recall di masa depan. Dengan kata lain, Pemilu adalah bentuk nyata dari pactum unionis (perjanjian kesatuan) dan pactum subjectionis (perjanjian penyerahan diri), di mana rakyat bersepakat membentuk tatanan politik sekaligus menyerahkan mandatnya pada penyelenggara negara. Dalam konteks pengesahan partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu, rakyat berperan sebagai juru kunci utama. Aturan mewajibkan setiap Parpol memiliki basis konstituen di berbagai tingkatan wilayah serta membuktikan militansinya melalui kepemilikan KTA. Prinsip kesukarelaan (voluntarysm) yang menjadi dasar keanggotaan partai menunjukkan ruang kebebasan rakyat untuk bergabung, tetapi begitu menjadi anggota, seseorang terikat pada statuta partai. Banyak partai akhirnya gagal memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu karena tidak mampu membuktikan legitimasi rakyat yang menjadi fondasi keberadaannya. Ketika tahapan pencalonan dimulai, ruang ekspresi rakyat semakin terbuka lebar. Hampir semua Parpol mengakomodasi beragam latar belakang calon, mulai dari politisi, akademisi, pengusaha, aktivis, buruh, ibu rumah tangga, budayawan, artis, hingga petani dan pekerja informal. Dengan modal KTA, peluang mencalonkan diri terbuka. Fenomena ini memperlihatkan Pemilu sebagai arena sosial yang menyatukan berbagai aspirasi rakyat. Namun, di balik keterbukaan itu, ada paradoks: keterlibatan rakyat yang tampak luas bisa saja hanya menjadi ornamen prosedural, di mana rakyat dijadikan obyek mobilisasi politik, bukan subyek yang sungguh berdaulat. Strategi Parpol dalam menyatukan kekuatan rakyat pada tahap pencalonan kerap memberi efek kejut pada hasil pemungutan suara. Banyak calon rela meninggalkan profesi mapan demi masuk ke gelanggang politik, seakan-akan jabatan hasil Pemilu adalah segalanya. Padahal jabatan itu hanya berlangsung lima tahun, dengan segala risiko hukum dan politik yang menyertainya. Pola ini memperlihatkan daya hipnosis Pemilu, tetapi sekaligus menyimpan bahaya ketika rakyat hanya diposisikan sebagai alat legitimasi formal tanpa dijamin ruang kontrol berkelanjutan. Di sisi lain, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) memikul tanggung jawab besar. Mereka mengkonsolidasikan hak rakyat menjadi daftar pemilih yang sah melalui kriteria ketat seperti usia, status pernikahan, kepemilikan identitas, dan ketidakikutsertaan sebagai aparat negara. Setiap deviasi dalam proses ini berpotensi menghilangkan hak rakyat untuk memilih, yang bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi dan sila keempat Pancasila. Ketika data pemilih kacau, kedaulatan rakyat terguncang, dan Pemilu berisiko kehilangan legitimasinya. Ekspektasi pasangan calon, Parpol serta calon anggota DPD terhadap kinerja penyelenggara Pemilu begitu besar, dengan menegaskan narasi “Suara Rakyat Suara Tuhan.” Narasi ini mengandung makna mendalam bahwa setiap suara harus dihargai sebagai mandat ilahi yang melahirkan legitimasi politik. Pada tahapan ini, posisi rakyat khususnya pemilih ditempatkan sebagai King and Queen, karena merekalah mandataris kedaulatan yang mewarisi hak untuk ikut memilih. Sedikit saja terjadi deviasi berpotensi menghilangkan hak pilih rakyat. Konsekuensi logis dari kelalaian mengelola data pemilih mengakibatkan hilangnya public trust. Dalam konteks yang lebih luas, penyelenggara Pemilu dianggap melakukan contempt of election berupa pelanggaran Konstitusi khususnya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila, pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kampanye kemudian menjadi ruang interaksi intensif antara rakyat dan peserta Pemilu. Secara ideal, kampanye menjadi wadah simbiosis mutualisme, tempat aspirasi rakyat bertemu dengan visi dan program politik. Namun, bila kampanye hanya dijalankan sebagai instrumen untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, maka rakyat kembali direduksi menjadi objek persuasi. Pada titik ini, ada bahaya bahwa Pemilu lebih berfungsi sebagai panggung pencitraan ketimbang arena pemberdayaan rakyat. Sistem proporsional terbuka memang menegaskan prinsip one man, one vote, one value. Nilai suara seorang buruh setara dengan nilai suara seorang presiden. Kesetaraan inilah yang membuat rakyat merasa terhormat, karena suaranya tidak kalah berharga dengan suara elite. Namun, sejarah Pemilu Indonesia menunjukkan partisipasi rakyat tidak pernah mencapai 100 persen. Angka partisipasi tertinggi justru terjadi pada Pemilu 1971 di era otoritarian dengan 96,6 persen, namun ironisnya ini adalah masa ketika demokrasi masih bersifat semu. Angka tinggi itu bukan lahir dari partisipasi sejati, melainkan dari kontrol negara yang kuat. Inilah gambaran paling jelas dari pseudo demokrasi, partisipasi rakyat hanya tinggi di atas kertas, tetapi nihil kedaulatan substantif. Kini, setelah DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-5 menyetujui 67 RUU prioritas, termasuk RUU Pemilu dan RUU Pemilihan Kepala Daerah, publik kembali mempertanyakan posisi rakyat. Apakah setelah kodifikasi UU ini rakyat tetap diposisikan sebagai pemegang kedaulatan, ataukah justru hanya sebagai penggembira demokrasi? Apabila revisi undang-undang lebih diarahkan pada penekanan teknokrasi prosedural seraya mengurangi ruang partisipasi substantif rakyat, maka yang akan lahir bukanlah demokrasi yang menghidupi rakyat, melainkan sebentuk pseudo demokrasi yang hanya menampilkan kulit luarnya. Demokrasi kehilangan vitalitasnya ketika kedaulatan rakyat dipersempit menjadi sekadar legitimasi formal, tanpa jaminan ruang artikulasi aspirasi yang otentik. Jika ditelisik lebih jauh pada substansi pasal-pasal yang berpotensi diubah, problematika segera tampak. Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) selama ini hanya berfungsi mengonsolidasikan dominasi partai besar dan menutup kemungkinan lahirnya alternatif politik baru. Konsekuensinya adalah rakyat kehilangan keberagaman pilihan, padahal pluralitas politik merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 yang menghapus threshold tersebut karenanya dapat dibaca sebagai koreksi historis. Namun, momentum ini masih menyimpan risiko. Bila revisi undang-undang justru kembali memasukkan mekanisme pembatasan lain yang pada hakikatnya menyerupai threshold, maka esensi putusan MK akan tereduksi, dan kedaulatan rakyat kembali dipersempit. Begitu pula wacana kembalinya sistem proporsional tertutup yang menempatkan daftar calon sepenuhnya dalam kendali elite partai. Langkah ini sesungguhnya menegasikan esensi kedaulatan rakyat, karena pemilih tidak lagi memiliki keleluasaan menentukan secara langsung siapa yang akan mewakili kepentingannya di parlemen. Lebih jauh lagi, apabila verifikasi partai politik diperketat tanpa disertai mekanisme yang inklusif, maka lanskap politik yang tercipta cenderung semakin oligarkis. Partai-partai kecil yang kerap menjadi kanal artikulasi bagi aspirasi alternatif rakyat akan kesulitan tampil dalam kontestasi. Padahal, keberadaan mereka justru penting sebagai penyeimbang hegemoni partai besar serta sebagai indikator sejauh mana demokrasi mampu menampung keragaman suara warga. Dengan demikian, revisi yang tidak sensitif terhadap dimensi kedaulatan rakyat berpotensi menggeser demokrasi Indonesia dari ranah substantif menuju prosedural semata. Semua ini berpotensi memundurkan kualitas demokrasi kita, menjadikannya hanya sebagai etalase prosedural yang indah dilihat, tetapi kosong makna. Bahaya pseudo demokrasi terletak pada kenyataan bahwa wajah luar tetap menampilkan mekanisme demokratis: Pemilu berlangsung, rakyat datang ke TPS, hasil diumumkan. Namun, di balik ritual itu, substansi kedaulatan rakyat perlahan terkikis. Demokrasi hanya menjadi pesta lima tahunan, sementara ruang kontrol rakyat di antara periode itu tertutup rapat. Rakyat sekadar dipanggil hadir sebagai legitimasi formal, tetapi suara kritisnya dibatasi, bahkan cenderung dibungkam. Oleh karena itu, revisi UU Pemilu bukan hanya soal harmonisasi regulasi, melainkan juga soal menjaga substansi kedaulatan rakyat. Penantian publik terhadap UU baru sejatinya adalah penantian terhadap jawaban, apakah bangsa ini setia pada amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, atau justru tergelincir kembali ke masa lalu ketika demokrasi hanya formalitas. Jika arah revisi menjauh dari rakyat, maka Pemilu Indonesia akan jatuh ke dalam pseudo demokrasi, hanya meriah di permukaan, tetapi kehilangan ruh kedaulatan di dalamnya.

Mengembalikan Trust dalam Pemilu Oleh Baharudin Hamzah Di bilik suara yang sunyi, suara sekecil apa pun punya arti. Pemilu, pada hakikatnya, adalah tentang trust. Rakyat percaya mandat itu akan dijaga, pemimpin percaya rakyat menggunakan suaranya dengan kesadaran. Begitu trust rapuh, pemilu hanya menjadi angka di atas kertas, pesta tanpa makna. Hari ini, tanda-tandanya terlihat jelas, transaksi menggantikan dialog, sensasi menenggelamkan gagasan, dan politik terasa seperti pasar malam, ramai tapi kosong. Karena itu, kita perlu kembali ke pertanyaan yang sering dilupakan, apa yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan ketika seseorang melipat surat suara? Plato, dua ribu tahun silam, sudah mengingatkan. Dalam The Republic, filsuf Yunani itu menulis bahwa politik bukan semata urusan prosedur, melainkan kualitas jiwa manusia. Demokrasi, katanya, mudah goyah ketika orang berhenti berpikir. Ketika suara tidak lagi lahir dari nalar, melainkan dari pesona, harta, atau retorika, maka demokrasi tak lebih dari arena hiburan. Dari sinilah awal kerusakan negara, bukan karena tirani pemimpin jahat, tetapi karena rakyat salah memilih. Pendidikan politik, bagi Plato, bukan pelajaran teknis, melainkan latihan mencintai kebenaran. Tanpa latihan itu, demokrasi menjadi pasar gelap: janji dijual, kebohongan laris, dan masa depan digadaikan pada kata-kata. Peringatan itu bukan sekadar kutipan klasik, ini nyata dalam denyut politik kita hari ini. Indonesia telah menyepakati pemilu sebagai jalan sirkulasi kekuasaan. Rakyat memilih DPR, DPD, DPRD, juga presiden dan kepala daerah. Kedaulatan dibunyikan melalui pemungutan suara langsung. Namun makna terdalamnya bukan ritus lima tahunan. Pemilu adalah peristiwa politik yang sakral untuk rakyat menitipkan kuasa. Titipan itu bernama trust. Ketika trust hadir, pilihan tidak ditentukan oleh amplop atau slogan, pilihan lahir dari nurani, dari ingatan pada rekam jejak, dari keyakinan bahwa mandat akan dijaga untuk kesejahteraan bersama. Sebaliknya, ketika trust lenyap, demokrasi hanya tinggal kulit. Politik dan Makna Trust: dari Plato ke Kesadaran Warga Plato memberikan kritik yang tajam bahwa bangsa yang malas berpikir akan menyerahkan masa depannya kepada pilihan yang keliru. Demokrasi tidak bisa hidup di antara rakyat yang pasif. Demokrasi hanya bernapas jika rakyat aktif menguji janji, mengkritisi retorika, dan mengenali wajah asli kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini menjadi lebih luas. Demokrasi kita relatif muda. Dalam hitungan sejarah, baru dua dekade lebih. Kita masih membawa warisan panjang budaya politik Orde Baru, budaya yang membentuk cara pandang pemilu sebagai kontestasi menang-kalah semata, bukan proses membangun kepercayaan. Dalam ingatan kolektif, pemilu identik dengan kampanye meriah, spanduk tinggi, arak-arakan, dan janji yang mudah dilupakan sehari setelah pencoblosan. Gagasan jarang benar-benar diadu, suara rakyat sering hanya menjadi target, bukan mitra dialog. Karena itu, pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Robert A. Dahl dalam Democracy and Its Critics (1989) menekankan bahwa partisipasi bermakna hanya mungkin lahir ketika warga punya akses informasi, ruang deliberasi, dan kemampuan menilai. Dalam konteks trust, pendidikan politik berfungsi seperti akar pada pohon demokrasi, tak terlihat di permukaan, tetapi menyangga seluruh batangnya. Jika akar ini rapuh, satu hembusan angin money politics atau populisme bisa merobohkannya. Pendidikan politik yang dimaksud bukan sebatas hafalan jadwal pemungutan suara atau pengenalan daftar calon. Pendidikan politik adalah proses panjang membangun kesadaran, mengenali perbedaan antara janji dan kebijakan, membedakan retorika dan rekam jejak, menilai siapa yang berkomitmen dan siapa yang hanya bersandiwara. Ketika publik memiliki kemampuan menilai dengan jernih, trust tumbuh secara alami. Sehingga trust yang lahir dari kesadaran jauh lebih kuat dibanding trust yang dibangun di atas retorika kosong. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak pemilih masih menempatkan politik sebagai ajang pragmatisme. Mereka memilih bukan karena yakin terhadap visi, melainkan karena ada imbalan sesaat seperti uang, sembako, atau sekadar janji jabatan kecil. Riset Rohi dkk. (2025) menunjukkan sebagian pemilih bahkan menunggu hingga detik terakhir sebelum menentukan pilihan, berharap ada “bantuan” finansial dari kandidat. Temuan ini sejalan dengan analisis Leonardo Vicente dan Leonard Wantchekon (2020), politik uang menggeser preferensi rasional ke preferensi transaksional. Akibatnya, trust terhadap sistem pemilu melemah. Pemilih tak lagi percaya politisi, politisi tak lagi percaya pemilih. Demokrasi menjadi transaksi, bukan kontrak kepercayaan. Keadaan ini juga berbahaya bagi kualitas kepemimpinan. Seorang pemimpin yang lahir dari transaksi akan menjalankan kekuasaan sebagai investasi, bukan amanah. Ia akan menghitung setiap kebijakan sebagai cara mengembalikan modal politik, bukan sebagai pengabdian kepada publik. Ketika trust hilang di awal, sulit berharap muncul trust di akhir. Kampanye, Arus Informasi, dan Erosi Trust Dalam teori komunikasi politik, kampanye adalah jantung pemilu. Everett M. Rogers dan J. D. Storey (1987) menyebut kampanye sebagai rangkaian aktivitas komunikasi terorganisir yang diarahkan untuk mendorong perubahan sosial dalam jangka waktu tertentu. Idealnya, kampanye adalah arena pertarungan gagasan, tempat publik diberi kesempatan untuk menimbang dan membandingkan visi, program, serta rekam jejak para calon. Dalam kenyataan kita, harapan itu sering jauh dari kenyataan. Dalam dua pemilu terakhir, kita menyaksikan kampanye yang lebih menyerupai pesta ketimbang ruang percakapan politik. Musik menggema, baliho membanjiri jalanan, namun gagasan tenggelam. Media sosial mempercepat arus informasi, tetapi sekaligus memperdalam kabut. Hoaks, potongan video tanpa konteks, dan propaganda beredar jauh lebih cepat daripada klarifikasi dan diskusi. Ketika informasi dikendalikan oleh emosi, bukan akal, trust tidak mungkin tumbuh. Orang lebih percaya pada kabar yang menyenangkan perasaan ketimbang data yang menenangkan pikiran, mereka terjebak dalam bubble-nya. Fenomena ini menciptakan spiral distrust. Pemilih merasa politisi hanya datang saat kampanye, maka mereka menuntut “imbalan” sebelum memberi suara. Politisi merasa pemilih tidak setia, maka mereka memilih jalan pintas dengan membeli suara. Dalam situasi ini, trust perlahan mati. Pemilu kehilangan makna sebagai momen kedaulatan rakyat dan berubah menjadi pasar besar. Sumber masalahnya juga terletak pada lemahnya rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Banyak kandidat maju bukan karena kapabilitas, tetapi karena kedekatan dan modal. Partai yang seharusnya menjadi sekolah politik justru sering menjadi gerbang transaksional. Ketika proses seleksi kandidat tidak meritokratis, publik sulit percaya. Ketika publik sulit percaya, trust semakin tipis. Politisasi identitas memperparah keadaan. SARA dijadikan alat kampanye, bukan batas etika. Polarisasi meluas. Masyarakat terbelah bukan oleh perbedaan gagasan, melainkan oleh label dan identitas yang dipertentangkan. Alexis de Tocqueville, dalam Democracy in America (1835), mengingatkan bahwa demokrasi bertahan bukan karena semua orang sepakat, tetapi karena mereka percaya pada mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan. Ketika kepercayaan itu retak, polarisasi tak lagi bisa dikelola. Pemilu menjadi pemicu luka, bukan perayaan kebangsaan. Situasi ini mengharuskan adanya counter-culture politik. Literasi digital dan politik menjadi benteng utama. Pemilih, terutama kelompok muda, perlu diberi ruang belajar untuk memilah kabar, memahami program, dan mendiskusikan masa depan. Media sosial seharusnya menjadi ruang deliberasi, bukan sekadar panggung amplifikasi kemarahan. Trust bisa tumbuh jika informasi jernih dan publik merasa dilibatkan secara bermakna. Menata Ulang Ekosistem: Kelembagaan, Pendidikan Pemilih, dan Politik Gagasan Mengembalikan trust dalam pemilu bukan tugas satu pihak, tetapi butuh kerja kolektif dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih. Penyelenggara memegang peran strategis. Peserta pemilu juga harus menata ulang panggung politik. Politik gagasan harus dikembalikan ke jantung kampanye. Calon pemimpin seharusnya bicara tentang kebijakan publik, soal pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, keadilan sosial, dan masa depan digital. Gagasan yang konkret dan terukur menunjukkan keseriusan. Gagasan yang konsisten melahirkan trust. Figur yang menampilkan gagasan kuat akan bertahan lebih lama daripada mereka yang hanya bersandar pada pesona sesaat. Masyarakat sebagai pemilih pun punya peran menentukan. Data KPU menunjukkan, pemilih muda, terutama generasi milenial dan Gen Z, mencapai 56% pada Pemilu Indonesia 2024. Kelompok ini memiliki daya ubah besar. Mereka terbiasa dengan teknologi, terbuka terhadap diskusi, dan tidak terlalu terikat pada patron lama. Jika mereka diberi pendidikan pemilih yang sungguh-sungguh, trust bisa dibangun dari lapisan terbawah demokrasi. Program “KPU Mengajar” yang digaungkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu pintu masuk yang strategis. Selama ini, sosialisasi pemilu lebih banyak berbicara soal tanggal pencoblosan dan hak-hak dasar. Itu penting, tetapi belum cukup. Mengajar berarti melibatkan warga dalam percakapan politik yang lebih dalam, soal bagaimana janji politik bisa diterjemahkan menjadi kebijakan, soal bagaimana kebijakan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Program ini membutuhkan perencanaan matang mengenai kurikulum, kelompok sasaran, jam belajar, metode partisipatif, serta mekanisme evaluasi. Indeks Partisipasi Pemilihan 2025 sekitar 61,94% di kabupaten/kota dan 60,97% di provinsi, memberi sinyal bahwa masih ada ruang luas untuk memperluas cakupan pendidikan pemilih. Trust tidak hanya tumbuh dari pidato dan baliho. Trust tumbuh dari kedekatan sehari-hari. Dari politisi yang hadir di luar musim kampanye. Dari penyelenggara yang transparan dalam langkah-langkah kecil. Dari warga yang mau belajar dan bertanya. Ketika tiga elemen ini saling bertemu, trust akan kembali mengisi ruang demokrasi. Politik gagasan pun perlahan akan menggantikan politik identitas. Publik akan lebih menghargai visi masa depan ketimbang atribut. Lebih tertarik pada rencana kebijakan ketimbang amplop. Lebih percaya pada konsistensi ketimbang pencitraan sesaat. Dalam atmosfer seperti ini, figur yang benar-benar dipercaya akan terpilih bukan karena retorika, tetapi karena integritas. Pemilu, pada akhirnya, hanyalah alat. Ruh dari alat itu adalah trust, kepercayaan yang mengikat rakyat dan pemimpin dalam satu simpul tanggung jawab. Rakyat menitipkan masa depan melalui selembar suara, pemimpin menerima titipan itu dengan janji untuk menjaganya. Bila trust dirawat, melalui proses yang jernih, kampanye yang mencerdaskan, dan warga yang kritis, pemilu tak lagi sekadar pesta lima tahunan tetapi menjelma peristiwa politik yang bermartabat. Melalui bilik suara, tempat segala hiruk-pikuk kampanye berakhir, rakyat berdiri sebagai pemilik tunggal kedaulatan. Di titik itu, suara bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah pesan. Pesan bahwa trust tidak bisa diperjualbelikan. Pesan bahwa masa depan tidak boleh ditukar dengan uang receh. Pesan bahwa hanya mereka yang benar-benar dipercaya, yang pantas menerima amanah..

Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan MK 135/2025: Momentum Memperkuat Demokrasi Lokal Oleh Elyaser Lomi Rihi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2025 menjadi titik penting dalam dinamika demokrasi elektoral di Indonesia, terutama dalam konteks pencalonan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menegaskan perlunya membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif dan transparan, dengan menempatkan prinsip kesetaraan politik sebagai landasan utama. Dalam amar putusannya, pembatasan yang bersifat eksklusif terhadap proses pencalonan bertentangan dengan prinsip konstitusional kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini tidak berdiri dalam ruang kosong, tetapi menjadi jawaban atas ketegangan yang telah lama mengiringi relasi antara demokrasi elektoral lokal dan oligarki partai politik. Secara substansial, keputusan tersebut memberikan sinyal kuat bahwa demokrasi lokal seharusnya menjadi ruang terbuka bagi partisipasi rakyat, bukan arena terbatas yang dikendalikan oleh segelintir elite. Dalam kerangka teori demokrasi, kebijakan yang memperluas hak pencalonan selalu berkaitan erat dengan gagasan partisipasi politik yang substantif. Seperti ditegaskan oleh Robert A. Dahl dalam karyanya Polyarchy: Participation and Opposition (1971), demokrasi modern hanya dapat bertumbuh jika warga negara memiliki akses nyata untuk ikut menentukan siapa yang memerintah dan bagaimana pemerintahan dijalankan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi bentuk koreksi terhadap struktur politik lokal yang selama ini cenderung tertutup dan hierarkis. Ketika pencalonan kepala daerah hanya dimonopoli oleh partai politik tertentu, proses demokrasi terancam kehilangan daya hidupnya. Pembukaan ruang bagi pencalonan yang lebih luas bukan sekadar langkah hukum, melainkan strategi politik untuk mengembalikan demokrasi lokal kepada rakyat. Di arena politik, konsekuensi dari putusan ini akan terasa langsung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Pencalonan bukan lagi sekadar soal memenuhi syarat administratif, tetapi menjadi penanda apakah demokrasi lokal sungguh-sungguh inklusif. Dalam konteks ini, kualitas calon pemimpin menjadi sangat krusial. Rekam jejak, integritas, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan akan menjadi faktor pembeda. Pemimpin yang dibutuhkan bukan hanya sosok yang populer, tetapi yang mampu membawa arah pembangunan jangka panjang. Seperti dikemukakan oleh Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay (2014), tata kelola yang baik sangat bergantung pada “the quality of leadership and state capacity”. Tanpa pemimpin berkualitas, demokrasi hanya akan berhenti pada ritual elektoral lima tahunan. Namun demokrasi elektoral lokal tidak dapat dilepaskan dari tantangan klasik yang terus menghantui proses pencalonan yakni politik uang, nepotisme, dan dominasi elite. Politik uang menggerus integritas proses demokrasi dan menjadikan kedaulatan rakyat sebagai komoditas transaksional. Nepotisme menutup peluang bagi calon alternatif yang sebenarnya memiliki kapasitas lebih baik. Transparansi pendanaan kampanye dan akuntabilitas politik menjadi benteng utama agar demokrasi lokal tidak direduksi menjadi arena perebutan kekuasaan yang sempit. Putusan MK 135/2025 membuka ruang hukum, tetapi keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh pengawasan masyarakat sipil, independensi penyelenggara pemilu, dan keberanian pemilih untuk tidak tunduk pada tekanan pragmatis. Kualitas demokrasi juga sangat bergantung pada kesadaran pemilih. Pemilih tidak boleh diposisikan sebagai objek kampanye, tetapi sebagai subjek politik yang menentukan arah kebijakan. Pemilih cerdas akan menilai calon berdasarkan gagasan, program, dan rekam jejak, bukan karena popularitas atau kedekatan personal. Literasi politik menjadi pondasi utama agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, media massa dan organisasi masyarakat sipil memegang peran penting dalam menyediakan informasi yang jernih dan objektif. Sebagaimana ditegaskan oleh Joseph E. Stiglitz dalam The Price of Inequality (2012), sistem demokrasi modern akan rapuh jika akses terhadap informasi dikendalikan oleh kelompok tertentu yang berkepentingan. Pencalonan kepala daerah juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip inklusivitas. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang bagi semua kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kaum muda, dan kelompok minoritas. Representasi politik yang luas memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan dan memperkuat legitimasi kepemimpinan. Putusan MK 135/2025 mengandung pesan bahwa demokrasi lokal bukan hak istimewa elite politik, tetapi hak politik setiap warga negara. Dalam konteks ini, partai politik dituntut untuk bertransformasi dari sekadar mesin elektoral menjadi lembaga rekrutmen politik yang terbuka dan meritokratis. Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan dimensi baru dalam pencalonan kepala daerah. Platform media sosial menjadi ruang kampanye utama, namun sekaligus membuka celah penyebaran disinformasi. Literasi digital menjadi prasyarat penting agar pemilih tidak mudah dimanipulasi opini politiknya. Teknologi dapat memperluas partisipasi, tetapi juga dapat mempercepat proses distorsi informasi. Karena itu, tanggung jawab calon pemimpin dalam menggunakan teknologi secara etis menjadi sangat krusial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2025 memberikan peluang besar untuk memperkuat demokrasi elektoral lokal di Indonesia. Namun peluang itu hanya akan menjadi kenyataan jika seluruh elemen masyarakat, partai politik, penyelenggara pemilu, dan pemilih benar-benar mengawal prosesnya. Demokrasi lokal tidak cukup hanya dijalankan, tetapi harus dijaga dari penyimpangan dan manipulasi. Seperti diingatkan Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America, “Democracy does not guarantee equality of conditions, but it guarantees equality of opportunity.” Ruang politik yang terbuka bukan jaminan lahirnya pemimpin baik, tetapi menjadi jalan bagi rakyat untuk memilih yang terbaik. Dari kota kecil, dari desa terpencil, masa depan demokrasi Indonesia sedang ditulis ulang melalui proses pencalonan kepala daerah. Putusan MK 135/2025 bukan sekadar teks hukum, melainkan momentum politik untuk mengembalikan demokrasi lokal kepada rakyat, tempat kedaulatan seharusnya berada.